
"Contextual Intelligence", Kecerdasan Pemimpin Atasi Krisis Multidimensi

ERA volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity (VUCA) memberikan ketidakpastian bagi siapapun, khususnya organisasi dan bisnis. Keadaan yang serba tidak pasti membuat kita harus adaptif dalam menyikapi keadaan.
Namun, yang paling penting adalah bagaimana kita tidak berhenti belajar dan melihat dari sudut pandang yang lebih besar. Konon, para inovator dunia memiliki kemampuan untuk melihat gambaran besarnya dan mampu memperkirakan sesuatu dengan akurat.
Contohnya Jeff Bezos. Tahun 1997, dia sudah memperkirakan akan terjadi booming di bidang e-commerce dan Jeff sudah mengantisipasi perubahan sikap konsumen dan sudah menetapkan bahwa Amazon akan menjadi pemain penting di bidang itu.
Nyatanya, foresight Jeff Bezos menjadi kenyataan. Amazon menjadi perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Pendapatannya mencapai 469 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 7.340 triliun, jauh melebihi perusahaan e-commerce lainnya.
Baca juga: Miliarder India Gautam Adani Salip Jeff Bezos, Jadi Peringkat 2 Orang Terkaya Dunia
Jeff Bezos pun ikut menuai kesuksesan yang diraih Amazon dan saat ini menjadi salah satu orang terkaya di dunia.
Kisah singkat ini mengilustrasikan salah satu karakter dari seorang pemimpin, selain visioner ia memiliki contextual intelligence, yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan sesuai konteks situasi yang dihadapi untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi.
Contextual Intelligence: Kemampuan wajib bagi pemimpin masa kini
Profesor Harvard, Tarun Khanna, memberikan pengertian tentang apa itu contextual intelligence. Menurut dia, contextual intelligence adalah sebuah kemampuan untuk memahami batas pengetahuan kita dan mengadaptasinya ke dalam bidang atau lingkungan yang berbeda.
Singkatnya, contextual intelligence adalah tentang bagaimana seorang pemimpin mengaplikasikan pengetahuannya di dalam kehidupan personal dan profesional.
Baca juga: Kepemimpinan Milenial
Sementara itu, Professor Harvard, Joseph Nye, melihatnya dari sudut pandang kepemimpinan, sehingga dia memunculkan istilah contextual leadership. Dia mengatakan bahwa contextual leadership sebuah kemampuan diagnosis intuitif yang dapat membantu pemimpin untuk menyelaraskan target dengan tujuan agar bisa menciptakan strategi yang cerdas.
Esensi penting dari kedua profesor di atas adalah bahwa pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk melihat konteks dari sebuah fenomena dan menerapkan pengetahuan yang mereka miliki untuk bisa menyelesaikan masalah.
Setiap pengetahuan tidak bisa diterapkan begitu saja dalam lingkungan apapun. Pemimpin perlu mencocokkan mana pengetahuan yang relevan dan mana yang tidak. Itulah yang disebut contextual intelligence.
Pemimpin dengan contextual intelligence yang baik memahami bahwa tidak ada solusi yang bersifat one-size-fits-all. Terlebih, dengan situasi dunia yang semakin kompleks. Alhasil, pemimpin harus memformulasikan sebuah kebijakan dan solusi yang berbasis konteks.
Kemampuan itu yang akan membantu pemimpin menyelesaikan berbagai permasalahan. Mereka layaknya seorang futurist yang memiliki kemampuan untuk membedakan tren yang berdampak dalam menghadapi kompleksitas.
Seorang futurist memiliki contextual intelligence yang baik dan menggunakan kemampuan diagnosanya untuk menentukan tren yang akan berpengaruh dan beradaptasi sesuai tren tersebut.
Contoh sederhananya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi pada hari ini. Ada berbagai cara untuk berkomunikasi: bisa melalui email, WhatsApp, media sosial, dan tatap muka. Akan tetapi, setiap platform memiliki cara dan etika yang berbeda-beda. Jenis pesannya pun berbeda.
Sangat penting untuk memahami bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif agar pesan kita tersampaikan. Itu adalah beberapa ilustrasi tentang bagaimana pemimpin perlu memiliki contextual intelligence yang baik.
Dengan kata lain, perlu menggunakan langkah-langkah yang disebutkan oleh Alvin Toffler: learn, unlearn, relearn. Penerapan contextual intelligence idealnya seperti itu. Seorang pemimpin menyeleksi pengetahuan, menentukan pengetahuan mana yang berguna, dan memutuskan untuk mempelajari sesuatu apabila pemimpin tidak memiliki set pengetahuan tertentu.
Namun untuk dapat melakukan itu perlu kecerdasan emosional. Regulasi emosi memang dibutuhkan, terlebih mendeteksi tren dan memanfaatkan tren yang terjadi membutuhkan kesabaran.
Tetapi, ketika kita berhasil, dampak yang akan didapat sangat besar. Manfaat kecerdasan emosional pun juga kerap kali digaungkan oleh para pakar kepemimpinan. Ketika sedang pandemi dan harus memimpin banyak orang secara remote, kemampuan ini sangat bermanfaat.
Riset dari Wittmer & Hopkins (2021) menyimpulkan bahwa pemimpin yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi akan mengalami tingkat stres yang lebih rendah dan stabil. Menurut McKinsey di tahun 2018, tuntutan untuk kemampuan emosional dan sosial akan tumbuh 26 persen di Amerika dan 22 persen di Eropa.
Riset dari Harvard Business Review tahun 2018 juga menemukan bahwa organisasi yang mengedepankan kecerdasan emosional 64 persen lebih berdaya dan toleran terhadap risiko. Karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa kecerdasan emosional adalah salah satu aspek terpenting bagi pemimpin yang memiliki contextual intelligence yang tinggi.
 Ilustrasi kepemimpinan di era digital.Memimpin dengan melihat konteks masalah
Ilustrasi kepemimpinan di era digital.Memimpin dengan melihat konteks masalah
 Ilustrasi kepemimpinan di era digital.
Ilustrasi kepemimpinan di era digital.Ron Ashkenas dalam artikelnya berjudul To Lead Change, Explain the Context di Harvard Business Review, memiliki nuansa yang menarik dalam menjelaskan contextual intelligence dalam memimpin.
Dia menekankan, memang dunia bisnis berjalan terlalu cepat dan strategi pasti berubah. Namun, seorang pemimpin perlu menjelaskan bagaimana fokus organisasi yang sekarang dapat membantu meraih visinya, sehingga, anggota rela untuk melakukan perubahan dan tetap berenergi.
Maksud Ron adalah bahwa setiap organisasi memiliki visi. Namun, untuk mencapai visi itu, ada beberapa misi yang harus dilaksanakan. Menurut Ron, perusahaan Hewlett Packard (HP) dulu memiliki tiga fokus yang membuat mereka berkembang: inovasi teknologi, lalu pertumbuhan melalui akuisisi, dan efisiensi.
Baca juga: Hewlett-Packard Enterprise Dikabarkan Bakal Dibeli Rp 523 Triliun
Strategi itu yang membawa HP ke tingkat yang sekarang. Poin pentingnya adalah setiap hal yang dilakukan itu bertujuan untuk meraih visinya dan pemimpin harus mengomunikasikannya secara transparan.
Hal itu akan membuat anggota merasa lebih paham dan lebih berenergi untuk bisa memberikan kontribusi terbaiknya. Anggota mengetahui kontribusinya dapat memberikan dampak positif bagi organisasinya.
Terlebih, menurut survei dari PwC tahun 2021, sebanyak 75 persen anggota ingin bekerja di organisasi yang memberikan dampak positif bagi lingkungan.
Di atas itu semua, menjadi lebih penting jika pemimpin dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan situasi yang dihadapi. Kata kuncinya adalah adaptif.
Menurut Profesor Ann Gregory dan Profesor Paul Willis dalam buku mereka yang berjudul Strategic Public Relations Leadership Second Edition, sulit bagi organisasi untuk selalu sukses setiap saat, sehingga membutuhkan adaptasi dan fleksibilitas terhadap dunia luar.
Adaptif berarti menyesuaikan gaya kepemimpinan kita dengan kondisi, apakah itu faktornya dari eksternal atau internal. Pemimpin yang memiliki contextual intelligence akan menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai situasi yang dihadapi.
Kemampuan adaptif ini tentu bermanfaat dalam mengatasi berbagai problematika global. Ada kemiskinan, pengangguran, perubahan iklim, dan masih banyak lagi masalah multidimensi kita.
Masalah-masalah tersebut tentu membutuhkan pemahaman berbagai isu dan sudut pandang. Misalnya, masalah ekonomi tidak hanya menjadi masalah sistemik yang melibatkan bagaimana sistem ekonomi berjalan, akan tetapi ada aspek kebijakan publik, pola pikir, politik, dan budaya yang harus dipahami.
Contoh nyatanya adalah tentang dunia perhumasan. Kita mengetahui betul bagaimana humas mengomunikasikan pesan mereka terhadap berbagai isu yang terjadi. Misalnya isu yang terjadi hari-hari ini tentang Covid-19 dan ginjal akut. Sosok humas yang baik harus mengetahui tentang Covid-19 dan ginjal akut dengan baik.
Baca juga: Performa Komunikatif Dalam Organisasi
Selain itu, menurut Profesor Ann Gregory dan Paul Willis, humas perlu mengetahui bagaimana mereka menyampaikan sense of urgency dalam isu menjadi sangat penting. Apakah harus menggunakan perspektif komunikasi risiko atau komunikasi krisis.
Pemilihan jenis komunikasi akan menentukan bagaimana respon masyarakat nantinya, apakah panik atau tetap tenang.
Menurut Profesor Ann Gregory dan Paul Willis dalam buku Strategic Public Relations Leadership Second Edition, untuk menjadi pemimpin hubungan masyarakat yang cerdas secara kontekstual, diperlukan apresiasi yang dinamis terhadap faktor-faktor yang membentuk kondisi yang berdampak pada organisasi mereka.
Contoh lainnya adalah banyaknya perusahaan gagal karena tidak mampu membaca situasi. Kita ambil contoh Kodak. Dahulu, tidak ada yang mampu mengalahkan Kodak dalam hal fotografi. Kualitasnya sangat bagus. Namun, mereka harus kalah karena disrupsi teknologi.
Baca juga: Sejarah Panjang Kamera Digital, dari VTR hingga Kodak
Pemimpinnya juga tidak mampu menyesuaikan kebijakannya dengan perkembangan zaman dan tidak memiliki contextual intelligence yang memadai.
Ilustrasi lainnya sudah kita rasakan. Ketika pandemi terjadi, cara kerja berubah dan prioritas anggota juga berubah. Anggota sekarang berfokus untuk mendapatkan work-life balance karena pandemi membuat well-being menjadi tidak baik-baik saja.
Tren itu bisa jadi berkelanjutan di masa depan, di mana sudah mulai ada istilah quite quitting dan sebagainya. Tidak hanya di tempat kerja, dunia pendidikan pun juga perlahan berubah karena teknologi.
Terlebih dengan banyaknya platform pembelajaran yang dapat diakses kapanpun dan di manapun. Cara belajar pun juga tidak hanya tatap muka. Ada pola hybrid atau full remote.
Untuk memberikan nuansa berapa pentingnya adaptabilitas, menurut studi dari Deloitte European Workforce 2020, sebanyak 40 persen karyawan tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan cara kerja di organisasi tempatnya bekerja saat Covid-19 menyerang.
Studi itu memberikan perspektif bahwa sikap adaptif penting, bukan hanya untuk anggota semata, melainkan pemimpin.
Selain itu, memimpin dengan konteks memerlukan tim yang solid serta memiliki latar belakang yang berbeda. Memiliki tim yang beragam latar belakang akan sangat membantu pemimpin meningkatkan contextual intelligence dan mengontekstualisasikan kebijakan dan lebih memahami persoalan, baik itu masalah internal dan eksternal.
Survei dari Gartner tahun 2020 menunjukkan tim yang inklusif berperforma 30 persen lebih baik. Terlebih, sekarang anggota senang berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang. Perasaan keterbukaan itu yang akhirnya menciptakan sense of belonging.
Tahun 2019, Harvard Business Review menulis laporan bahwa sense of belonging akan meningkatkan performa sebesar 56 persen, mengurangi turnover sebanyak 50 persen, dan akan lebih sedikit orang yang absen dari pekerjaan mereka.
Di atas itu semua, menurut saya sense of belonging akan menciptakan trust. Trust akan menciptakan tim yang berani untuk berbicara fakta.
Steve Andriole dalam artikelnya di Forbes menekankan pentingnya truth-talking teams. Untuk menciptakan tim yang berani menyatakan fakta, kepercayaan harus dibangun lebih dahulu agar orang-orang nyaman berbicara fakta.
Tim yang berbasis kepercayaan akan membuat anggota lebih engage, yang menurut riset Gartner tahun 2020 akan meningkat sebesar 76 persen. Tetap terpaku pada visi, tetapi caranya bisa bervariasi tergantung target yang ingin dicapai.
Mengkomunikasikan apa yang dilakukan saat ini akan berdampak di kemudian hari juga vital agar anggota tetap semangat dalam bekerja. Namun, tidak lupa juga untuk lebih melihat ke dalam sisi anggota apa yang mereka butuhkan dan rangkul tim agar tercipta sense of belonging.
Sense of belonging dapat menciptakan tim yang berani bicara fakta. Aspek ini penting dalam menyelesaikan masalah multidimensi.
Pentingnya konteks untuk memecahkan masalah multidimensi
Menjadi pemimpin yang memiliki contextual intelligence membutuhkan banyak latihan, pengalaman, dan pengetahuan, terutama bagaimana menempatkan pengetahuan yang tepat sesuai konteksnya.
Yang terpenting menurut Profesor Ann Gregory dan Paul Willis dalam buku Strategic Public Relation Leadership Second Edition adalah mengumpulkan data dan menggunakannya untuk memitigasi dampak terburuk.
Kita bisa belajar banyak dari isu perubahan iklim yang masih melanda dan bagaimana perlunya contextual intelligence dalam mengatasi berbagai isu yang disebabkan perubahan iklim. Terlebih, banyak sektor yang merasakan dampak dari perubahan iklim.
Secara umum, studi IPCC tahun 2022 memperkirakan bahwa ada sekitar 32 - 132 juta orang yang akan masuk dalam kemiskinan ekstrem. Selain itu, 3,3 - 3,6 miliar orang hidup di dalam negara yang sangat rawan dampak iklim.
Melihat betapa menyeramkan dampak perubahan iklim, pemimpin perlu step up dan menggunakan kepiawaiannya dalam banyak hal. Misalnya bagaimana menghasilkan kesepakatan antar negara.
Perubahan iklim bukan murni masalah lingkungan. Ada banyak konteks politik yang terlibat di dalamnya. Negosiasi, lobi politik, dan proses lainnya agar dapat menciptakan kebijakan publik yang ramah terhadap lingkungan.
Terlebih, ketika dihadapkan pada berbagai kepentingan negara, pemimpin perlu mencari jalan tengah yang bisa memuaskan kepentingan para aktor.
Selain masalah perubahan iklim, masalah pangan juga sifatnya multidimensi dan memiliki kaitan erat dengan perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak pada pasokan rantai makanan global.
Asian Development Bank (ADB) menggelontorkan dana sebesar 1,4 miliar dollar untuk mengatasi masalah jangka pendek dan jangka panjang keamanan pangan pada periode 2022- 2025.
Selain itu, riset Agnolucci & Lipsis (2019) menemukan bahwa cuaca buruk membuat 30 persen pertumbuhan pangan yang diharapkan menjadi gagal di Eropa.
Menyelesaikan masalah pangan bukanlah perkara mudah karena banyak variabel yang saling memengaruhi. Ada ekonomi, fertilitas tanah, cuaca, kebijakan publik, dan lain-lain.
Pendekatan sistemik dan inovatif adalah pilihan satu-satunya agar dapat menyelesaikan isu ini. Ada beberapa aktor yang telah menghasilkan inovasi di sektor pangan.
Ada satu inovasi dari pemulia kacang dari Aliansi Penelitian Kacang Pan-Afrika. Mereka berhasil mengembangkan model riset berdasarkan permintaan yang telah menghasilkan 500 varietas kacang baru sesuai kebutuhan, selera, dan preferensi.
Ini hanyalah salah satu dari contoh bagaimana pemimpin melihat masalah dari gambaran yang lebih besar dan mengambil peluang untuk berinovasi.
Kita ambil contoh kasus lain, yaitu pada saat pandemi. Penanganan pandemi sangat sulit dilakukan karena kebijakan yang diambil akan berdampak pada ekonomi, politik, sosial-budaya, dan lain sebagainya.
Misalnya saat memutuskan kebijakan pembatasan sosial atau PPKM. Pemberlakuan PPKM bergantung pada level keparahan Covid-19. Jika parah, maka akan diberlakukan PPKM level 3 atau 4. Apabila keadaan di suatu daerah mulai membaik, akan diberlakukan level 1 atau 2.
Level dalam PPKM memberikan ruang gerak bagi pelaku ekonomi agar dapat beraktivitas kembali, setidaknya memberikan harapan bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik jika daerah menaati protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi.
Contoh kasus di atas memberikan kita beberapa benang merah. Pemimpin perlu adaptif dan melihat segalanya dari kacamata yang lebih besar. Hal itu akan membantu pemimpin menganalisis langkah apa yang tepat dilakukan di sektor A, B, C, dan lain-lain.
Tidak semua kebijakan dapat berlaku di semua sektor. Akan tetapi, semua pengetahuan berguna jika diaplikasikan sesuai konteks masalah.
Poin pentingnya adalah bahwa agar dapat menjadi pemimpin yang memiliki contextual intelligence yang tinggi, tiga kemampuan yang disebutkan Profesor Ann Gregory dan Profesor Paul Willis dalam Strategic Public Relations Leadership Second Edition sangat vital untuk dimiliki.
Pertama, kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan dengan mengubah suatu bagian dari diri pemimpin.
Kedua, kemampuan untuk mengubah konteks lingkungan untuk menciptakan kecocokan yang lebih baik.
Ketiga, kapasitas untuk mengenali tanda kapan harus berpindah dari satu konteks ke dalam konteks lainnya yang lebih rewarding.
Saya pikir, pemimpin dengan contextual intelligence yang kuat akan membawa organisasi di masa depan menuju kesuksesan. Mereka juga akan menjadi problem solver yang multidimensi. Saya yakin kualitas ini dimiliki oleh pemimpin muda Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.-
![]()
Piknik Luar Angkasa ala Miliarder Jeff Bezos
-
![]()
Update Daftar Orang Terkaya di Dunia Versi Forbes, Bos LV Bernard Arnault Geser Jeff Bezos
-
![]()
Daftar 5 Orang Terkaya di Dunia 2021, Elon Musk Geser Jeff Bezos
-
![]()
Jebakan Kepemimpinan yang Buruk, Pesan untuk Gen Z
-
![]()
Gaya Kepemimpinan Bonek untuk Pos Indonesia
-
![]()
Belajar dari Kepemimpinan Gautam Adani, Orang Terkaya Nomor 2 di Dunia
-
![]()
Urgensi Kepemimpinan Sadar Bencana
-
![]()
Kepemimpinan Milenial




















![[POPULER TREN] ICC Ajukan Surat Penangkapan Pemimpin Israel dan Hamas | Mengintip Jasa](https://asset.kompas.com/crops/thxfZvt6ob2iNqQ-VPdZR-vv0EU=/0x3:689x463/170x113/data/photo/2024/05/21/664ccaccd90e2.jpg)






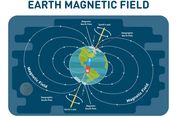












![[POPULER TREN] Pencairan Jaminan Pensiun Sebelum Waktunya | Prakiraan Cuaca BMKG 24-25 Mei](https://asset.kompas.com/crops/VQxgG5k8641fH13UxTS8JxhvE6E=/205x83:1069x659/177x117/data/photo/2024/05/24/6650a8e45dfb0.jpg)


















