Urgensi Pemikiran Yudian Wahyudi tentang Keselarasan Pancasila dan Syariah Islam
Berbeda dengan para pemikir Islam dan Pancasila kawakan, seperti KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) atau Prof Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang bersifat generalis, pemikiran Yudian tentang Islam dan Pancasila lebih bersifat teknis. Hal ini disebabkan pendekatannya yang bersifat metodologis, melalui filsafat hukum Islam (ushul fiqh) dengan gagasan utama, yakni tujuan utama syariah (maqashid al-syari’ah).
Tulisan ini merupakan rangkuman inti dari buku karya penulis sendiri, yakni Islam dan Pancasila, Perspektif Maqashid Syariah Prof KH Yudian Wahyudi, PhD yang terbit pada Agustus 2022. Buku ini merupakan kajian terhadap pemikiran keislaman dan Pancasila dari Yudian, terutama berdasarkan pada paparan Yudian tentang Pancasila sebagai Kalimatun Sawa’ di Harvard University tahun 2003.
Ketegangan historis
Letak urgensi pemikiran Yudian Wahyudi adalah pada kemampuannya untuk meleraikan ketegangan antara Islam dan Pancasila yang bersifat historis. Historisitas yang dimaksud adalah ketidakpuasan sebagian tokoh Islam atas rumusan Pancasila resmi, akibat dihapusnya sila Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dari Pancasila.
Hal ini mengemuka, terutama di sidang Konstituante tahun 1956-1959. Para tokoh Islam bergabung dalam “faksi Islam”, mengusulkan Islam sebagai dasar negara, sebagai alternatif bagi Pancasila. Dalam rangka pengajuan Islam ini, para tokoh tersebut menafikan Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat sekular.
Misalnya, pimpinan Masyumi, Mohammad Natsir menyebut Pancasila sebagai ideologi sekular (la diniyyah), karena tidak bersumber dari wahyu. Hal ini membuat nilai-nilai Pancasila tidak memiliki kepastian konseptual, sehingga bisa ditafsiri oleh perspektif apapun. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya, menurut Natsir, bukan cerminan dari doktrin Islam, karena sumber dari Pancasila bukan Al Quran.
Natsir lalu menyitir penjelasan Soekarno tentang sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Kursus Pancasila pada 26 Mei 1958 yang bersifat antropologis, bukan teologis. Artinya, Soekarno menjelaskan sila ketuhanan Pancasila sebagai cerminan dari tradisi ketuhanan bangsa Indonesia yang menjulur panjang, bahkan hingga ke pra-Hindu-Buddha. Menurut Natsir, ini menandakan bahwa ketuhanan di dalam Pancasila, bukan bagian dari tradisi Islam, tetapi tradisi semua agama, termasuk agama non-monoteis. (Natsir, 2001: 23)
Ketidakpuasan juga dialami para tokoh Islam perumus Piagam Jakarta. Kahar Muzakkir, mantan anggota Panitia Sembilan, yang berpidato di Konstituante menyayangkan penghapusan “tujuh kata” Piagam Jakarta, dan menyatakan bahwa Pancasila telah dikebiri (Natsir, 2001: 95). Artinya, menurut Mudzakkir, semestinya, rumusan Pancasila mengacu pada rumusan Piagam Jakarta dengan sila “ketuhanan bersyariah”. Rumusan ini adalah kesepakatan luhur antara kelompok Islam dan kelompok kebangsaan, demi tercapainya konsensus nasional. Akan tetapi, menjelang sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, “tujuh kata” dihapus, sehingga rumusan Pancasila pun dikebiri.
Ketidakpuasan juga dilayangkan oleh penghapus “tujuh kata” itu sendiri, yakni Mr. Kasman Singodimedjo yang berpidato dalam Konstituante tersebut (Natsir, 2001: 234). Pada 18 Agustus 1945 pagi hari, Mr. Kasman, bersama dengan Kiai Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo dan Teuku Muhammad Hasan terlibat rapat dengan Bung Hatta untuk menghapus “tujuh kata” tersebut. Di Konstituante, Mr. Kasman menyesali hal itu, sehingga menarik dukungan terhadap Pancasila dan menawarkan Islam sebagai penggantinya.
Menjaga syariah
Berbeda dengan ketidakpuasan kelompok Islam dalam Konstituante, Yudian menegaskan bahwa penghapusan “tujuh kata”, tidak berarti penghapusan syariah dari Pancasila. Dalam paparan Islam dan Nasionalisme: Sebuah Pendekatan Maqashid Syariah (2019: 35), Yudian menemukan penggunaan kaidah fikih dalam proses penghapusan “tujuh kata” tersebut. Penggunaan kaidah fikih ini digunakan oleh Kiai Wahid Hasyim yang merupakan tokoh NU dan akrab dengan metode fikih.
Menurut Yudian, penghapusan “tujuh kata” yang merupakan prinsip ketuhanan bersyariah Islam tidak otomatis menghapus syariah Islam dari Pancasila. Mengapa? Karena Kiai Wahid menggunakan kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu (apa yang tidak bisa didapatkan semua, jangan ditinggalkan semua).
Artinya, ketika syariah Islam tidak bisa ditegakkan di dalam dasar negara, maka nilai-nilai Islam tidak boleh terhapus sama sekali dari dasar negara. Menurut Yudian, yang terjadi justru sebaliknya: syariah telah diganti dengan prinsip tauhid yang tercermin dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tauhid yang merupakan akidah, ialah sumber dari syariah. Dengan demikian, meskipun redaksi syariah telah dihapus dari Pancasila, namun substansi syariah tetap dijaga oleh akidah tauhid di dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pembacaan Yudian ini selaras dengan keputusan NU di era Konstituante tersebut. Meskipun pada awalnya para tokoh NU yang mewakili Partai NU mengusulkan Islam sebagai pengganti Pancasila. Akan tetapi, sikap ini kemudian direvisi oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengusulkan jalan tengah dalam bentuk rumusan “Pancasila-Islam”. Sebuah rumusan yang mengajukan Pancasila dengan penempatan Piagam Jakarta sebagai “dokumen historis” (bukan dokumen yuridis) yang menjiwai dasar negara nasional tersebut.
Rumusan jalan tengah ini lalu diusulkan oleh Kiai Wahab Hasbullah dalam sidang Konstituante 1959, dan disetujui oleh faksi Islam. Rumusan PBNU ini pula yang diterima oleh Presiden Soekarno sehingga menerbitkan Dekrit Presiden No. 150 tanggal 5 Juli 1959. Isi dekrit tersebut ialah instruksi kembali pada UUD 1945 dan Pancasila, dengan Piagam Jakarta sebagai dokumen historis yang menjiwai UUD dan Pancasila.
Dekrit Presiden 1959 yang terinspirasi dari rumusan “Pancasila-Islam” ala PBNU ini selaras dengan analisa Yudian, bahwa di dalam Pancasila, syariah Islam tetap terjaga. Hal ini disebabkan oleh penegasan Piagam Jakarta sebagai nilai yang menjiwai Pancasila. Inilah yang membuat Indonesia sebenarnya merupakan negara nasional bersyariah Islam, tentu bagi umat Islam. Hal ini membuat segenap upaya untuk mengislamkan Indonesia, dalam bahasa fikih, bersifat “mengadakan sesuatu yang sudah ada” (tahsilul hasil). Artinya, Indonesia sudah Islami dan syar’i; mengapa harus diislamkan dan disyariahkan?
Langkah penyelarasan
Pembacaan Yudian terhadap hubungan Pancasila, syariah dan tauhid tersebut merupakan jalan keluar dari pembenturan antara Pancasila dan syariah Islam. Artinya, ketika sebagian kelompok Islam masih mengidealkan Piagam Jakarta karena memuat syariah, maka pandangan tersebut sebenarnya tidak diperlukan, karena menurut Yudian, syariah tidak hilang di dalam Pancasila. Hal ini disebabkan oleh keberadaan tauhid dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan sumber bagi syariah. Dengan demikian, alih-alih Pancasila telah meniadakan syariah; yang terjadi justru sebaliknya, bahwa Pancasila bagi umat Islam, bersifat melindungi syariah karena ia memuat nilai tauhid.
Pemahaman bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan tauhid dikembangkan oleh Kiai Wahid Hasyim. Pemahaman ini lalu diajukan Kiai Wahid kepada Ki Bagus Hadikusumo, sehingga Ki Bagus juga memiliki pandangan serupa. Soal Kiai Wahid mengajak Ki Bagus memaknai sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai cerminan tauhid diinformasikan oleh tokoh Muhammadiyah yang terlibat dalam rapat tanggal 18 Agustus 1945, yakni Mr. Kasman Singodimedjo (1982: 129).
Selain menegaskan kandungan syariah dalam Pancasila, Yudian juga merumuskan keselarasan syariah Islam dan Pancasila, melalui beberapa langkah.
Pertama, menyamakan sifat Pancasila dan syariah yang memiliki dualitas nilai. Dualitas nilai tersebut mengacu pada sifat keduanya yang Ilahi pada satu sisi, serta duniawi (wadl’i) pada saat bersamaan. Artinya, alih-alih Pancasila hanya bersifat duniawi (sekular), ia justru merupakan dasar negara yang bersifat ilahi sekaligus duniawi. Demikian pula, alih-alih syariah Islam hanya bersifat ilahi; ia bersifat ilahi sekaligus duniawi. Mengapa? Karena selain memuat sila-sila kemanusiaan dan kebangsaan yang duniawi, Pancasila juga memuat sila ketuhanan yang ilahi. Demikian pula, selain merupakan hukum Allah SWT, syariah Islam adalah hukum Tuhan yang diperuntukkan bagi manusia, serta melibatkan “metodologi manusia” (tafsir, qiyas, ijma’) dalam mengamalkan syariah tersebut.
Dualitas Pancasila sebagai “yang ilahi” dan “yang duniawi” ini merupakan gagasan yang tidak asing, sebab Mr. Muhammad Yamin dalam Sistema Filsafah-Pantjasila (1958) misalnya, memiliki gagasan serupa. Menurut Yamin, di dalam Pancasila terdapat filsafat ketuhanan yang bersumber dari wahyu (sila Ketuhanan YME), sekaligus filsafat kemanusiaan yang bersumber dari rasionalitas.
Hanya saja, Yudian lalu memperjelas gagasan ini melalui tradisi pemikiran hukum Islam, yang ia dasarkan pada kritiknya terhadap pemikiran Hasan Hanafi tentang sekularitas syariah Islam. Menurut Hanafi, syariah bersifat sekular karena ia memuat nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana berkembang di Eropa Abad Pencerahan. Bagi Yudian, gagasan ini bersifat ekstrem, karena selain memuat sekularitas (bukan sekularisme), syariah juga bersifat ilahiah. Kritik Yudian terhadap pemikiran Hasan Hanafi ia tulis dalam Is Islamic Law Secular? A Critical Study of Hasan Hanafi’s Legal Philosophy. Tulisan tersebut ia paparkan di Harvard Law School pada 4 Desember 2003.
Gagasan Yudian tentang Pancasila yang bersifat dualitas ilahi-duniawi ini bisa menjadi jalan keluar dari pembenturan Islam dan Pancasila, karena dasar negara ini dihakimi sebagai sesuatu yang hanya bersifat sekular.
Kedua, penyelarasan Pancasila dengan maqashid al-syari’ah. Menurut Yudian, maqashid al-syari’ah memuat tiga tujuan, yakni tujuan yang bersifat niscaya (maqashid al-dlaruriyyah), tujuan yang bersifat kebutuhan (maqashid al-hajiyyah) dan tujuan yang bersifat ornamental (maqashid al-tahsiniyyah). Ketiga tujuan ini bersifat kesatuan. Dalam hal ini, maqashid al-dlaruriyyah memuat lima perlindungan hal-hal yang niscaya dalam kehidupan manusia, yakni perlindungan terhadap agama (hifdz al-din), perlindungan nyawa (hifdz al-nafs), perlindungan akal (hifdz al-‘aql), perlindungan keturunan (hifdz al-nasl) dan perlindungan harta (hifdz al-maal).
Dalam konteks inilah, nilai-nilai Pancasila mencerminkan berbagai prinsip maqashid al-syari’ah tersebut, yakni semua sila Pancasila mencerminkan maqashid al-dlaruriyyah, seperti sila ketuhanan (hifdz al-din), sila kemanusiaan (hifdz al-nafs), sila kebangsaan (hifdz al-nasl), sila demokrasi (hifdz al-a’ql), dan sila keadilan sosial (hifdz al-maal). Kelima sila ini pun terangkum dalam ketiga jenis maqashid tersebut, yakni sila kebangsaan (persatuan nasional) dan sila demokrasi merupakan maqashid al-hajiyyah yang dibutuhkan untuk menopang perwujudan maqashid al-dlaruriyyah dari kelima sila Pancasila.
Artinya, tanpa persatuan bangsa (keamanan dan ketentraman) serta demokrasi, maka perwujudan nilai-nilai Pancasila yang merupakan perwujudan dari hak-hak asasi manusia, tidak akan terjamin. Selanjutnya, Pancasila itu sendiri merupakan maqashid al-tahsiniyyah, atau tujuan ornamental dari pelaksanaan maqashid al-syari’ah di Indonesia. Sebagai istilah dan konsep, Pancasila merupakan “bentuk lokal” dari pengamalan maqashid al-syari’ah di Indonesia, yang tidak terdapat di negara-negara muslim lainnya.
Dalam kaitan ini, Pancasila meluas, tidak hanya sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, tetapi menjadi bagian dari khazanah pengamalan syariah Islam di Indonesia. Hal ini tentu masuk akal, sebab akar kata Pancasila sendiri berasal dari khazanah keagamaan, yakni Buddha, dimana Pancasila pada awalnya berarti lima moralitas Buddhisme.
Ketiga, reorientasi fikih Indonesia dalam rangka kontekstualisasi hukum Islam ke dalam sistem hukum modern di Indonesia. Gagasan ini Yudian rumuskan dalam tesisnya di McGill University, Kanada pada 1993, dengan judul Hasbi’s Theory of Ijtihad in the Context of Indonesia Fiqh. Tesis tersebut mengkaji gagasan fikih Indonesia dari ahli fikih Nusantara, Hasbi Ash-Shiddieqy. Tesis Yudian mengembangkan gagasan Hasbi tentang ijtihad bi al-ra’yi (ijtihad dengan akal) melalui qiyas (analogi), berdasarkan prinsip kemaslahatan (maslahat), kebaikan (istihsan) dan tradisi (‘urf).
Yudian lalu mengembangkan gagasan itu dengan merumuskan metode ijtihad jama’i (ijtihad kolektif) melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai perwujudan dari lembaga perumus hukum Islam dalam sejarah Islam, yakni ahl al-halli wa al-‘aqd (ahwa). Ijtihad kolektif ini lalu membentuk ijma’ jama’i (konsensus kolektif) pada level kenegaraan.
DPR sebagai “ahwa” ini telah melahirkan banyak perundang-undangan bernuansa syariah. Baik syariah secara formal, seperti UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, hingga Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pembentukan hukum Islam juga dilakukan dalam kerangka maqashid al-syari’ah, di mana berbagai UU yang melindungi hak-hak dalam maqashid al-dlaruriyyah, Yudian masukkan dalam kategori hukum Islam, meskipun secara formal bukan merupakan hukum Islam.
Misalnya, perlindungan terhadap akal dan harta dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Bahkan UU No. 14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga merupakan hukum Islam, karena ia melindungi nyawa yang dijaga oleh maqashid al-syari’ah. (Yudian, 1995: 55-58)
Dalam kaitan ini, DPR-MPR beserta produk perundang-undangan yang lahir darinya, Yudian tempatkan sebagai produk ijma’ jama’i di Indonesia. Itulah yang membuatnya sampai pada kesimpulan, bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi merupakan otoritas hukum tertinggi bagi umat Islam. Hal ini didasarkan pada prosedur perumusan hukum Islam melalui qiyas dan ijma’ berdasarkan prinsip kemaslahatan, kebaikan dan tradisi.
Artinya, sistem hukum modern di Indonesia, beserta tata negaranya, telah “diislamkan” oleh Yudian berdasarkan metodologi perumusan hukum di dalam Islam. Dalam konteks inilah, sistem hukum modern yang menaungi syariah dan maqashid al-syari’ah tersebut berdiri di atas norma dasar hukum Pancasila.
Dari uraian di atas, terlihat bahwa Yudian Wahyudi telah mengembangkan hubungan Pancasila dan syariah Islam secara keilmuan. Hal ini disebabkan pendekatannya terhadap syariah yang bersifat ilmiah, melalui pendekatan filsafat hukum Islam (ushul fiqh). Hubungan Pancasila dan syariah yang bersifat ilmiah ini yang telah meleraikan ketegangan antar-keduanya. Satu ketegangan yang sampai sekarang belum bisa dileraikan oleh kelompok Muslim yang memahami syariah sebagai ideologi, bukan sebagai ilmu. Inilah letak vital urgensi pemikiran Kepala BPIP, Prof Kiai Haji Yudian Wahyudi, PhD.
https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/28/114106065/urgensi-pemikiran-yudian-wahyudi-tentang-keselarasan-pancasila-dan-syariah

















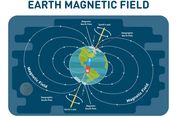












![[POPULER TREN] Pencairan Jaminan Pensiun Sebelum Waktunya | Prakiraan Cuaca BMKG 24-25 Mei](https://asset.kompas.com/crops/VQxgG5k8641fH13UxTS8JxhvE6E=/205x83:1069x659/177x117/data/photo/2024/05/24/6650a8e45dfb0.jpg)












