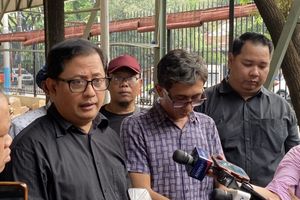Gas Air Mata di Sekolah Rempang: Potret Pendidikan Tak Penting di Indonesia

REMPANG, Batam mencekam. Persoalan agraria menjadi isu klasik bumi pertiwi yang selalu membenturkan hak masyarakat adat dengan ideologi program pembangunan serta modernisasi.
Masyarakat dari 16 desa setempat menolak proyek strategi nasional Eco City. Sehingga aparat gabungan dikerahkan untuk pengosongan lahan. Alhasil, bentrok tidak dapat dihindari.
Salah satu yang mendapat sorotan publik adalah masuknya gas air mata ke sekolah di dekat area bentrok.
Dari beberapa sumber berita dan video beredar, tampak anak sekolah berhamburan keluar dan berlari ke hutan untuk menghindari terpaan gas air mata.
Beberapa juga dilaporkan pingsan dan harus dirawat di IGD terdekat. Aparat gabungan gagal mengantisipasi dampak tersebut.
Dampak lanjutan kejadian ini adalah rasa trauma dan bayangan masa lalu kelam. Semua akan terekam jelas dalam benak dan memori para siswa. Bagaimana ketenangan dan kedamaian belajar mereka terusik.
Di kelas mereka belajar tentang bela negara, nilai sila ke lima Pancasila. Namun saat bersamaan, tetangga atau bahkan kedua orangtua mereka sedang disemprot water canon dan gas air mata oleh aparat negara hanya karena mempertahankan hak tanah adatnya. Para siswa melihatnya sendiri kejadian represif tersebut.
Mobil-mobil baja berdatangan membawa nama-nama modernisasi dan pembangunan. Sementara rumah dan tanah nenek moyang mereka adalah pertaruhannya. Pelajaran apa yang sedang dipertontonkan aparat dan negara pada generasi muda bangsa ini?
Pembelajaran kontekstualitas jadi tidak relevan
Kemendikbudristek beserta seluruh jajaran boleh saja berteriak Merdeka Belajar dan pentingnya pembelajaran kontekstualitas.
Pembelajaran yang baik adalah kesadaran terhadap lingkungannya tumbuh, berdampak pada masyarakat sekitar, memaksimalkan sumber daya alam setempat. Namun di lapangan harapan tersebut lebih banyak jadi pepesan kosong.
Dalam kasus agraria Rempang, kita dapat sama-sama melihat kalkulasi pendidikan diletakkan di gerbong terakhir.
Menembakkan gas air mata dengan tidak menjadikan letak sekolah sebagai pertimbangan merupakan kalkulasi yang buruk.
Mereka para aparat sejatinya hanya sedang menjalankan tugas yang berorientasi kalkulasi ekonomi, investasi, dan pembangunan. Tidak ada nama rakyat di sana. Kalaupun ada, rakyat yang mana?
Aparat negara gagal mempertimbangkan kepekaan lingkungan dan kondisi geografi. Akibatnya mereka gunakan cara berpikir primitif seperti menyalahkan arah angin sehingga asap masuk ke sekolah.
Mana kalkulasi kemanusiaan dan pendidikan dalam kejadian tersebut? Apa tidak ada musyawarah berdasarkan antropologi dan ekologi?
Bayangkan, bila sampai para siswa yang jadi korban membaca pernyataan “Gas Tertiup Angin” tersebut, upaya guru atau pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa lewat penalaran logika dan kritis, menjadi tidak berguna.
Karena di depan sorot kamera pun, aparat negara masih dengan percaya diri mempertontonkan pikiran dangkal yang rendah argumen dan tanggung jawab. Para siswa yang berlari ke hutan, akhirnya melihat semua ini sebagai rekam jejak pelajaran nyata.
Belajar dari Stasiun Kami-Shirataki, Jepang
Kita perlu sedikit banyak belajar pada persoalan di Jepang perihal kalkulasi pendidikan. Stasiun Kami-Shirataki yang terletak di Pulau Hokkaido selama tiga tahun telah mengalami penurunan jumlah penumpang yang signifikan.
Operator Japan Railway (JR) telah merencanakan penutupan stasiun ini, mengingat lokasinya yang terpencil serta berhentinya pengiriman kereta kargo di sana.
Namun, putusan tersebut diubah ketika JR mengetahui adanya siswi Sekolah Menengah Atas yang setia pergi pulang sekolah menggunakan layanan kereta tersebut.
JR memutuskan untuk mengurungkan niat penutupan dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga stasiun tetap beroperasi.
Bahkan, mereka menyesuaikan jadwal kereta dengan jadwal siswi SMA tersebut. Stasiun Kami-Shirataki dengan JR telah mengambil komitmen untuk menjaga operasional stasiun ini hingga siswi SMA tersebut menyelesaikan pendidikannya.
Dari keadaan tersebut, dapat kita pahami bahwa kalkulasi pendidikan diletakkan terdepan melampaui budaya, lingkungan, apalagi ekonomi.
Pikiran untung rugi benar-benar hampir tidak diperlihatkan. Sekalipun secara peraturan dan perhitungan akomodasi biaya jelas bertentangan, namun mereka lebih percaya bahwa pendidikan jauh dari segalanya.
Mungkin dari kalkulasi ekonomi, hal tersebut lebih banyak ruginya. Karena mengoperasikan kereta hanya untuk satu penumpang di tiap hari.
Namun sayangnya pemerintah Jepang mengesampingkan kalkulasi seperti itu. Orientasi kebutuhan pendidikan untuk generasi muda diprioritaskan melebihi apapun. Diletakkan pada titik terdepannya.
Sangat tidak mengherankan bila itu terjadi, mengingat setelah diluluhlantahkan dengan bom atom saja, justru guru yang lebih dipikirkan oleh Jepang. Ini cerminan budaya yang luar biasa dalam menghargai, menjalankan, dan mengapresiasi pendidikan.
Harusnya kalkulasi semacam itu yang dikedepankan oleh aparat dan negara dalam persoalan agraria Rempang.
Bukankah mereka dengan sadar tahu lokasi bentrok terdapat sekolah dan pemukiman penduduk? Mereka sebenarnya bekerja dan bertugas untuk kepentingan siapa?
Kalaupun sudah jelas ada begitu banyak massa menghadang di depan, bukankah sebaik-baiknya langkah adalah mundur dan mengedepankan musyawarah ulang?
Sayangnya, cerminan luar biasa seperti yang Jepang lakukan hampir tidak pernah dipertontonkan negara Indonesia.
Seluruh pejabat Indonesia, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, semuanya selalu mempertontonkan ketamakan dan orientasi perut.
Mereka lebih suka berdalil dan berlindung di balik aturan perundang-undangan dan hitung-hitungan jabatan politik perintah.
Sehingga tanggung jawab etik dan pikiran aksiologi selalu jadi slogan pinggiran yang cuma digaungkan saat kampanye pemilu.
Dalam kasus gas air mata yang masuk ke sekolah cukup memperlihatkan bahwa memang pendidikan rasanya “tidak penting” di Indonesia ini.
Bahkan sejak kasus rempang beserta video represi itu beredar pun, Nadiem Makarim belum memberi sikap. Padahal jajaran kementerian pendidikan sedang gembar-gembor promosi merdeka belajar.
Mentok dalam kasus-kasus begini, sekolah akan diliburkan. Bukankah ini juga sama saja mengurangi hak para siswa mendapat waktu belajar yang sama?
Apakah merdeka belajar itu selalu urusan administrasi, konten, dan apresiasi? Apa jaminan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman wilayah tidak masuk implementasi merdeka belajar?
Apa yang terjadi di Rempang cukup menunjukkan bahwa semua bergerak dan bertugas atas dasar perintah konglomerasi.
Tidak ada pembelajaran kebudayan, kebhinekaan, kebangsaan, apalagi olah pikir pendidikan di sana. Hal ini perlu kita renungkan bersama sebagai bangsa. Di mana sebenarnya kita melatakkan fungsi dan peran pendidikan?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.