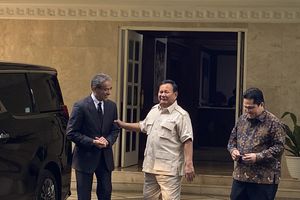Kriteria Pemimpin yang Layak Mengelola Kampus
Di samping itu, perguruan tinggi juga mengemban tanggung jawab mulia dalam membentuk karakter bangsa melalui pendidikan dan menjadi salah satu sektor penting yang menentukan masa depan dan majunya suatu bangsa.
Dalam upaya mengembalikan perguruan tinggi kepada marwahnya, salah satu hal yang harus dipertimbangkan adalah pemilihan pimpinan, terutama yang memegang posisi-posisi strategis dan penting di kampus, seperti rektor dan dekan.
Seorang pimpinan kampus memegang peran penting terutama terkait kemajuan institusi, berjalannya Tridharma Perguruan Tinggi, dan yang terpenting lagi adalah keberlangsungan (sustainability) kampus di masa depan.
Pemimpin cerdas, kreatif, dan visioner
Mempertimbangkan rekam jejak seorang pemimpin adalah hal wajib karena jika salah memilih, masa depan dan reputasi perguruan tinggi akan menjadi taruhannya.
Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan (leadership) dan konsep yang visioner dan jelas. Hal itu tercermin dalam visi-misinya.
Pemimpin dengan kualitas ini mampu melihat peluang dan mengembangkan strategi berdasarkan analisis yang matang dan terukur untuk keberlangsungan institusi.
Hal ini penting karena dunia terus mengalami perubahan tren dari waktu ke waktu sehingga kebutuhan terhadap pasar juga berubah-ubah.
Oleh karena itu, pimpinan kampus harus adaptif, kreatif, dan inovatif dalam mengoptimalkan keilmuan yang telah ada untuk berkontribusi maksimal sesuai dengan kebutuhan publik.
Contoh lain, jika harus membuka program studi baru, seorang pimpinan perguruan tinggi, terutama Perguruan Tinggi Swasta (PTS) juga harus memiliki dasar studi kelayakan dan analisis SWOT yang terukur.
Pimpinan harus mempertimbangkan banyak aspek seperti relevansi dan kontribusi program studi dengan kebutuhan keilmuan saat ini serta bagaimana prodi tersebut bisa berdampak positif terhadap sustainability kampus.
Jangan sampai program studi tersebut menjadi ‘beban’ baru bagi suatu institusi, mengingat PTS bersifat otonom terutama dalam tata kelola keuangan.
Selain itu, seorang pemimpin harus bersikap profesional. Sikap profesional yang dimaksud adalah kemampuan membangun kultur lingkungan kerja yang akademis, nyaman, dan bebas dari segala bentuk tekanan yang bersifat feodalistik.
Profesional juga bisa diartikan tidak menggunakan jabatan untuk ‘bertangan besi’ dan bersikap sewenang-sewang terhadap dosen, pegawai, dan mahasiswa.
Kultur kerja di perguruan tinggi tidak sama dengan korporat yang masih banyak memberlakukan kultur kerja berdasarkan senioritas atau atasan-bawahan (meskipun tidak semua).
Sepatutnya, kultur kerja yang bersifat kolegial dijaga dan dipelihara di kampus karena hal ini nantinya akan berdampak positif pada fungsi dan peran perguruan tinggi.
Kegagalan pimpinan dalam membangun kultur profesional dan kolegial di kampus tentunya akan berdampak pada munculnya konflik dan ketidaknyamanan bekerja. Nantinya berpotensi terhadap menurunnya produktivitas kerja.
Selain itu, seorang pemimpin yang profesional pasti jeli dalam memilih orang-orang yang kompeten untuk mengisi posisi-posisi penting di kampus.
Ia pasti akan memilih orang berdasarkan kualitas, kapasitas, dan kompetensi, bukan berdasarkan unsur kedekatan apalagi kepentingan politik dan KKN.
Mengapa demikian? Karena menjalankan fungsi dan peran kampus adalah pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan, kreativitas, integritas, kedispilinan, dan kemampuan analitik.
Oleh karena itu, jika memilih orang dengan kualitas kinerja yang buruk, ini akan berdampak negatif terhadap kemajuan dan akreditasi institusi serta berpotensi menimbulkan public distrust.
Tidak hanya itu, aspek kejujuran, rekam jejak kinerja, dan pengalaman dalam pengelolaan organisasi adalah hal penting yang harus diperhatikan dalam memilih pimpinan.
Jika bakal calon pemimpin pernah memiliki rekam jejak buruk seperti terkait dengan praktik KKN, maka sudah selayaknya tidak dipilih karena nantinya akan berisiko bagi keberlangsungan perguruan tinggi.
Tidak ada ruang gaya diktator dan antidemokrasi
Sejatinya kampus adalah ruang yang terbuka dengan ragam pemikiran dan kritis terhadap segala kepentingan politik dan kekuasaan yang merugikan.
Seluruh insan kampus harus diberikan kebebasan berpendapat jika ada kebijakan maupun hal-hal yang bersifat merugikan.
Oleh karena itu, seorang pimpinan kampus harus benar-benar memastikan bahwa budaya demokratis terpelihara.
Tidak ada budaya yang bersifat menjajah karena sesungguhnya tidak ada tempat bagi diktator di kampus.
Dalam tulisannya berjudul Saatnya Reformasi Perguruan Tinggi, dosen sosiologi politik FIS UNJ, Ubedila Badrun berpendapat bahwa praktik antidemokrasi mulai banyak ditunjukkan oleh beberapa penguasa kampus, terutama dalam membuat kebijakan kampus.
Hal ini sangat ironis, karena kampus harusnya menjadi contoh model penerapan demokrasi di Indonesia.
Secara substantif, demokrasi dalam kaitannya dengan menentukan pemimpin harus memenuhi tiga hal: partisipasi khalayak, stabilitas pemerintahan, dan ketertiban politik yang menjunjung tinggi regulasi (G. Bingham Powell Jr. dalam buku Contemporary Democracies, Participation Stability, and Violence, 1982)
Badrun menambahkan, kriteria demokratis di lingkungan kampus terpenuhi apabila terdapat prinsip partisipatif, kebebasan akademik, sikap terbuka terhadap kritik, dan terwujudnya pelembagaan demoraktis dalam struktur dan birokrasi kampus.
Kasus gugatan Dewan Guru Besar UI tentang Statuta UI-PP No. 75 Tahun 2021 yang dinilai cacat formil dan materiil dan hanya menguntungkan kelompok elite kampus tertentu adalah salah satu contoh nyata dari pelanggaran prinsip demokrasi yang terjadi di lingkungan kampus (Kompas, 27/07/2021).
‘Nyawa’ universitas yang tercermin dalam statuta didesain sesuai kepentingan kelompok elite tertentu.
Dan parahnya, selain terjadi penyalahgunaan kekuasaan, fungsi dan peran senat akademik dan organ penting kampus lainnya diabaikan dalam penyusunannya.
Di sisi lain, sangat disayangkan sekaligus memprihatikan bahwa di Indonesia pernah terjadi kasus kriminalisasi akademisi hanya karena menuliskan kritik dan pendapatanya terhadap kebijakan kampus, seperti yang terjadi pada Saiful Mahdi (Kompas, 2/09/2021).
Sehingga, sudah saatnya kepemimpinan yang sentralistik, diktator, represif, dan antikritik diakhiri.
Selain mencedari prinsip kampus sebagai ruang kritis dan demokratis, hal ini juga berpotensi menekan kreativitas dosen dan mahasiswa karena salah satu ‘kemewahan’ yang dimiliki insan kampus adalah kritik dan pemikiran.
Untuk menghindari hal ini, pemimpin harus menjamin terdapatnya ruang diskursus pemikiran selebar-lebarnya karena ‘asupan’ terbaik bagi insan kampus adalah sikap kritis dan kebebasan berpendapat.
Jika dua hal tersebut absen dari priotitas pemimpin dan kampus resisten terhadap kritik, yang terjadi adalah ‘pengkerdilan’ prinsip kampus.
Kondisi itu hanya menjadikan insan-insan kampus sebagai ‘budak-budak’ yang menghamba pada kekuasaan semata.
Terkait dengan pencegahan budaya dan praktik antidemokrasi di kampus, segenap sivitas akademika juga harus diberikan hak untuk bersikap kritis terhadap segala aturan-aturan kampus (misalnya, statuta dan kebijakan-kebijakan pimpinan).
Hal itu demi mencegah terbukanya peluang bagi hadirnya perilaku otoriter dan praktik KKN dalam mengelola kampus yang hanya menguntungkan kelompok tertentu saja.
Oleh karena itu, seorang pimpinan kampus harus dipilih berdasarkan mekanisme dan sistem demokratis serta memiliki legitimasi, bukan dari penunjukkan yang diduga sarat dengan kepentingan.
Jika ini terjadi di kampus, kita pantas mempertanyakannya. Jangan sampai terjadi.
https://www.kompas.com/edu/read/2022/03/07/054500671/kriteria-pemimpin-yang-layak-mengelola-kampus