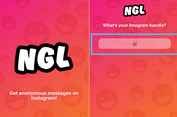Alasan Mengapa Orang Kaya Tetap Sulit Bahagia
Konten ini merupakan kerja sama dengan Kompasiana, setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.com

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Paradoks Kemajuan: Alasan Mengapa Orang Kaya tetap Sulit Bahagia"
KOMPAS.com - "Ilusi-uang" merupakan istilah yang melukiskan fenomena mayoritas orang yang mulanya menganggap uang dapat memuaskan mereka, tapi justru yang mereka dapatkan hanyalah ketidakpuasan lainnya yang sebelum itu tidak pernah terpikirkan.
Kini kita mendapati fenomena itu sebagai sesuatu yang marak terjadi pada orang-orang "besar", dan ini adalah kesempatan bagi mereka yang malas untuk berkata, "Uang tidak memberimu kebahagiaan.
Meskipun terdengar konyol dan tampak seperti pelarian, tetapi petuah tersebut tidak sepenuhnya keliru.
Dalam sebuah makalah yang diterbitkan awal tahun 2018, seorang peneliti memberikan kesimpulan yang mengejutkan bahwa "sepanjang spektrum pendapatan-kekayaan, pada dasarnya semua orang mengatakan (perlu) dua atau tiga kali lipat" untuk benar-benar bahagia.
Baca juga: Rusia Kehilangan Ribuan Jutawan, Ini Negara-negara Baru yang Jadi “Safe Haven” Bagi Orang Kaya
Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa semakin kaya kita, semakin kita menjadi kurang bahagia. Studi tersebut menemukan bahwa ketika kita mencapai pendapatan rumah tangga tertentu ($95.000 per tahun dalam skala global), tingkat kepuasan dan kesejahteraan hidup semakin rendah.
Apa yang salah? Bagaimana mungkin kelimpahan uang, berdasarkan banyak fenomena yang terjadi, malah mendatangkan lebih banyak ketidakpuasan? Apakah Bumi sedang berputar ke arah yang berlawanan?
Paradoks Kemajuan
Emile Durkheim pernah mengatakan bahwa semakin nyaman dan etis sebuah masyarakat, semakin pikiran kita membesar-besarkan kesembronoan yang sepele. Sederhananya, jika semua perampok berhenti mencuri, kita tidak akan merasa bahagia begitu saja.
Kita akan merasa sama kecewanya ketika menghadapi hal-hal yang lebih kecil.
Secara paradoksal, melindungi orang dari permasalahan atau kesulitan tidak akan membuat mereka lebih bahagia atau lebih aman; itu justru membuat mereka menjadi lebih mudah untuk merasa tidak aman.
Fenomena itulah yang menjadi titik kerangka Paradoks Kemajuan: semakin membaik keadaan, semakin peka diri kita terhadap banyak ancaman, sekalipun kenyataannya tidak ada satu pun.
Paradoks Kemajuan tidak hanya berlaku untuk individu atau golongan tertentu, melainkan semua orang yang juga tidak terbatas pada masalah uang. Kita mendapati paradoks ini dalam peradaban kita sendiri; peradaban yang sekilas tampak lebih baik daripada masa sebelumnya.
Kemajuan besar dalam bidang teknologi, kedokteran, komunikasi, dan segalanya dalam beberapa abad terakhir justru telah menciptakan lebih banyak masalah dan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi bagi orang-orang.
Kita memang hidup di zaman yang menarik. Secara material, segalanya tampak sangat baik melebihi zaman-zaman sebelumnya. Kendatipun begitu, entah mengapa segala-galanya tampak kacau balau dan benar-benar sulit.
Kita melihat Ilmu Psikologi semakin berkembang serta populer, dan secara sekilas memang sungguh baik. Tetapi itu juga disebabkan oleh salah satu efek samping yang tidak kita harapkan, bahwa manusia kontemporer semakin rapuh secara psikologis.
Kemajuan material dan keamanan tidak secara otomatis membuat kita tenang atau membuat kita lebih mudah untuk menaruh harapan di masa depan. Sebaliknya, barangkali dengan perkembangan yang mengagumkan ini, orang justru lebih menderita.
Kita menjadi lebih egois dan kekanak-kanakan. Kita menjadi lebih manja daripada generasi sebelumnya, dan karena itulah kita lebih rapuh dalam menghadapi berbagai persoalan sepele yang memenuhi keseharian kita.
Sebuah penelitian oleh Harvard University menemukan adanya kelemahan yang dimiliki banyak orang dalam memecahkan masalah. Mereka menyebut hasil temuannya dengan "prevalence-induced concept change", suatu konsep yang sebenarnya sejalan dengan Paradoks Kemajuan.
Konsep mereka sedikitnya menunjukkan bahwa ketika prevalensi suatu masalah berkurang, manusia secara alami cenderung untuk mendefinisikan kembali masalah itu sendiri.
Hasilnya adalah, ketika masalah menjadi lebih kecil, konseptualisasi orang tentang masalah itu menjadi lebih besar yang kemudian membuat mereka tidak menyadari kenyataan bahwa mereka telah memecahkannya.
Kejanggalan tersebut menimpa banyak orang kaya sehingga apa yang mereka dapatkan hanyalah ketidakpuasan lainnya.
Mereka berangkat dengan asumsi sederhana bahwa uang membantu mereka mendapatkan kesenangan. Mereka benar, tetapi kesenangan yang dibawa uang sering kali tidaklah lama, dan mereka pun segera menginginkan lebih banyak uang untuk kesenangan yang juga lebih banyak.
Jadi, mereka terus bekerja karena mengira bahwa uang akan menenangkan jiwa mereka yang gundah akibat ketakutan dan ketamakan. Tapi, uang tidak bisa melakukannya.
"Kenyataannya, alasan banyak orang kaya itu menjadi kaya bukanlah karena hasrat," tulis Robert Kiyosaki dalam buku populernya Rich Dad Poor Dad, "melainkan rasa takut. Mereka meyakini bahwa uang bisa menyingkirkan rasa takut miskin, jadi mereka menimbun berton-ton uang, hanya untuk mendapati bahwa ketakutan itu semakin parah. Mereka sekarang takut kehilangan uang."
Kekeliruan terbesar dari orang kaya adalah, mulanya mereka berangan-angan bahwa menjadi kaya dapat membantu mereka untuk menderita sesedikit mungkin.
Namun ketika akhirnya mereka menjadi kaya, mereka baru belajar bahwa kelimpahan harta adalah penderitaan juga; penderitaan dalam bentuk yang berbeda.
Penderitaan ada di kondisi mana pun, tetapi titik mana pun selalu dapat menjadi lebih baik. Penderitaan selalu ada di sana; yang berubah hanyalah persepsi kita tentang penderitaan.
Segera setelah kehidupan kita "membaik", harapan kita berganti menjadi lebih kompleks, dan kita kembali merasa sedikit tidak puas.
Lebih banyak uang, lebih banyak keinginan. Itu sama seperti berhadapan dengan lorong gelap yang panjang tiada berujung. Kita dipaksa untuk terus berlari tanpa pernah tahu di mana kita bisa menjumpai secercah cahaya. Pada dasarnya, kita terjebak dalam kegersangan makna.
Tentu Paradoks Kemajuan (atau apa pun konsep yang serupa) bukanlah alasan kita untuk menghindari kekayaan dan lantas berkata dengan ekspresi menyebalkan di depan wajah miliarder, "Uang tidak memberimu kebahagiaan."
"Bagaimanapun," tulis Robert Kiyosaki, "menghindari uang itu sama gilanya seperti terikat pada uang." Kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih masuk akal: bagaimana cara menjadi kaya yang bahagia?
Kekayaan yang membahagiakan tidak didorong oleh rasa takut, sebab bila demikian, seberapa banyak pun uang yang kita miliki, itu hanya akan memperbesar rasa takut kita pada akhirnya.
Emosi manusia yang dikuasai oleh rasa takut dapat menjadi "malapetaka" dari segala kemajuan material, karena hal itulah yang membuat semakin tingginya rasa takut akan kehilangan.
Kita cenderung menunjukkan reaksi emosional yang negatif, karena sejatinya, pikiran kita sering membesar-besarkan (atau menyepelekan) permasalahan kita untuk menyesuaikannya dengan tingkat stres yang ingin kita rasakan.
Pada akhirnya, orang akan mengalami pergeseran dari "keinginan materi" menjadi "keinginan yang berarti", di mana hasrat terhadap materi telah berubah menjadi hasrat akan makna; sesuatu yang secara mental jauh lebih menyehatkan.
Orang kerap mengira bahwa menjadi kaya adalah "puncak kehidupan" di mana mereka dapat memeroleh kesejahteraan dan hanya tinggal menikmati kehidupan dengan bahagia. Tetapi perihal "puncak kehidupan", agaknya tidak ada yang layak disebut demikian selain kematian.
Saya percaya bahwa yang benar bukanlah kaya untuk bahagia, tapi bahagia untuk kaya. Seneca pernah berkata, "Bukan orang yang memiliki sedikit, tetapi orang yang menginginkan lebih banyak ... itulah yang miskin."
Memang tidak mudah untuk merasa cukup dalam kondisi di mana diri kita sendiri merasa sedang kekurangan sesuatu. Tetapi bila kita mampu melakukannya, kitalah orang kaya yang sesungguhnya; itulah kebijaksanaan yang kita harapkan di dunia kontemporer ini.
Artinya, diperlukan keseimbangan antara pengetahuan finansial dan eksistensial. Maksud saya, kita tidak hanya dituntut untuk cerdas perkara uang, tetapi juga kehidupan tentang mengenal diri sendiri, alam semesta, dan Tuhan.
Baca juga: Dalam 5 Tahun, Orang Kaya Indonesia Diramal Bakal Naik 60 Persen
Saya percaya bahwa dengan membiasakan diri untuk merasa puas dalam kekurangan, kita dapat lebih mudah untuk merasa berkecukupan. Ini memang tidak nyaman pada mulanya, tetapi seiring waktu, kita akan menikmatinya.
Seperti ketika kita pergi ke gym: kita mengencangkan otot-otot kita dengan cara yang melelahkan dan kadang menyakitkan. Tetapi kita tahu bahwa semua itu memang harga yang layak dibayar untuk melahirkan kekuatan dan ketangguhan.
Hukum yang yang sama berlaku untuk kehidupan. Tidak hanya menjadi kaya, karena menjadi kaya tidak memecahkan semua masalah. Yang terpenting adalah, kemampuan kita untuk mengelola kehidupan kita sendiri dan menikmatinya selama matahari masih menyinari kita.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.