
Mendaras Zaman Kiwari

VIRUS dan vaksin yang telah menjadi tema perbincangan kita sejak akhir 2019 lalu, secara berangsur mulai dilupakan.
Hagia Sophia yang lama tertidur dalam rahim peradaban, malah kembali mencuat ke permukaan sejarah umat beragama. Graha monumental peninggalan Romawi ini memang dirancang sebagai vulgata.
Lalu Dinasti Ottoman memasjidkannya melalui keputusan Al-Fatih (Sultan Mehmed II). Turki modern lantas memuseumkan segala riwayat tersebut, dan Presiden Erdogan tiba-tiba mengikuti lagi jejak leluhurnya.
Dunia Kristen pun geger seketika. Alhasil, arkaik peradaban besar itu hanya sekadar ajang perebutan sentimen keberagamaan sahaja.
Sampai awal Juli 2020 ini, ternyata kita masih berkutat pada sebuah keadaan yang lama mengendap dalam bawah sadar manusia terkini. Ribuan tahun perjalanan agama langit, rupanya belum juga menumbuhkan kesadaran baru.
Agama kian terselubungi ikonoklastik, dogma semu, doktrin palsu. Sinagog, gereja, atau masjid, padahal bukan bagian ultim dari agama.
Bangunan itu produk kebudayaan manusia. Ia bisa berubah atau tetap. Tergantung bagaimana konsep yang kita sepakati sepanjang keberadaannya di lintasan peradaban.
Setelah setengah abad lebih manusia terasing dari dan di dalam rumahnya sendiri, alam kembali mengajak kita pulang.
Pandemi dan kita
Pandemi yang sedang bersiap tinggal landas meninggalkan kita, turut berjasa mengajari manusia tentang begitu banyak hal yang kadung ia lupakan.
Rumah dan keluarga kita kembali semarak. Kehangatannya terasa hingga ke sumsum tulang belakang. Suami-istri menemukan lagi arti ikatan perkawinan mereka. Orangtua dan anak mulai saling menyadari fungsi mereka dalam keluarga.
Ada begitu banyak hal yang telah berlangsung selama berbulan lamanya kita mendekam di rumah. Pola hidup, pranata kehidupan, cara berpikir, prilaku sosial, serta laku keberagamaan, pelahan tapi pasti, mulai beranjak ke periode baru yang belum pernah terbayangkan sama sekali.
Presedennya tak sempat kita kenali. Internet yang selama satu dasawarsa ini hanya berguna untuk berselancar informasi-data, ternyata sudah berada di garda depan untuk mengurusi hajat hidup manusia sedunia.
Mata pencaharian, cara kita belajar, bergaul, berkeluarga, bertumbuh, beragama, bernegara, berbangsa, telah berubah total.
 Ilustrasi.
Ilustrasi.Google berhasil mengajak miliaran manusia bekerja dengan hanya berbekal kegemaran semata.
Kita tak perlu lagi memburuh bermodal selembar ijazah. Cukup merekam dan mengunggah. Menjaring penonton yang berlangganan sebanyak mungkin. Maka perusahaan apa pun akan berlomba mengiklankan produk mereka di akun Anda.
Penjelajahan manusia pada semesta dirinya, terpantik lagi setelah sekian lama mati suri.
Betulkah demikian?
Sayangnya, penjelajahan itu tidak alamiah. Pola pikir kita melulu diarahkan untuk memercayai kata viral sebagai sebuah kenyataan yang sumir.
Kehancuran sebuah negara berdaulat, cukup dipicu satu cuitan di media sosial. Amuk massa bisa seketika meledak tak terduga. Perang berkecamuk hingga sampai di titik kebosanan.
Alhasil, derita pun tak lagi mengundang simpati dan empati. Perang sudah menjadi kewajaran. Lumrah adanya. Pertikaian dan perbalahan anak manusia gagal menemukan makna.
Kegagalan memaknai itu mungkin juga baru diinsyafi banyak orang setelah menyadari udara kita jauh lebih segar.
Sungai di Venesia dan di kota-kota megapolitan lain mulai dikunjungi angsa. Laut kita lebih bersih. Jutaan ribu hektar hutan mulai ditumbuhi tanaman dengan sendirinya.
Namun saat yang sama, manusia sebagai penyintas waktu, kadung menumpuk sampah pikiran dan perasaan yang jumlahnya sudah begitu mengkhawatirkan.
Setidaknya sampai tulisan ini kami susun, kita belum punya piranti peleburan sampah model begitu.
Belum lagi sempat melakukan perbaikan dari kerusakan parah yang kita buat sendiri, sekonyong-konyong dunia telah bersalin rupa dengan segala borok yang diidapnya selama ini.
Puncak kemanusiaan
Abad-21 yang melindas kita sedemikian cepat, abai kita mafhumi berdasar apa yang pernah diwariskan Sosrokartono dan Einstein—pada Abad-19 dan 20: Guru terbaik manusia adalah dirinya sendiri. Murid terbaik manusia, ya dirinya sendiri.
Saat ini yang kian merajalela terjadi, malah sebaliknya—dan cenderung lebih mengerikan. “Guru” manusia adalah deretan piksel yang tiada berjiwa. Beku, angkuh, dan acuh pada noumena.
Wajar bila kemudian pengetahuan pada era ini sebatas fenomena belaka. Bahkan menjadi ilmu pun belum. Apalagi yang lebih luhur dari itu.
Ilmu dan pengetahuan yang dikembangkan masyarakat modern, celakanya malah berujung pada saintifikasi belaka. Harus terverifikasi, positif, logis, matematis.
Padahal bagaimana membuat tolok ukur pengalaman bathin manusia? Apa perangkat yang hendak dipakai untuk menakar kandungan perasaan dan kedalaman hati kita? Bagaimana pula caranya memindai pencapaian spiritual?
Kebanalan begini saja sudah bikin kita repot bukan kepalang.
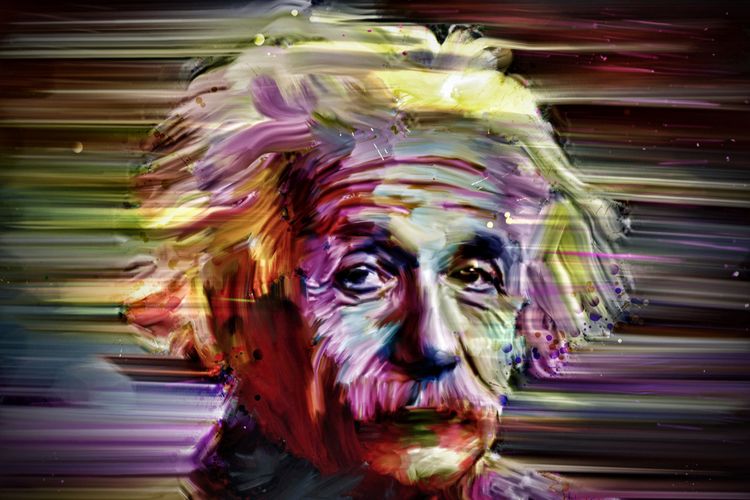 Albert Einstein.
Albert Einstein.Einstein dengan Teori Relativitas-nya, juga hendak mengatakan hal yang tak jauh beda dengan Sosrokartono.
Apa yang kadung dijadikan postulat oleh para saintis, senyampang masih teori, berpeluang diruntuhkan.
Einstein sudah membuktikan itu manakala ia merobohkan mekanika kuantum Newton, sembari menikmati cerutu dan menyeruput kopi di beranda rumahnya.
Jangankan teori ilmiah, waktu saja relativ dalam ruang. Ia begitu tapi bukan itu. Ia begini namun bukan ini. Ia sebagaimana adanya yang harus kita pahami.
Dengan bahasa lain yang mungkin belum pernah terucapkan oleh Einstein hingga akhir hayatnya, ia ingin berkata, “Bukan itu yang sesungguhnya, dan temukanlah ada apa di balik itu...”
Kekayaan
Sekadar contoh saja. Beberapa orang terkaya Indonesia dan dunia, semakin kaya-raya dengan adanya pandemi.
Sementara miliaran manusia lain hidup tunggang langgang demi melanjutkan kehidupan mereka.
Pertanyaan kita, lantas apakah yang sudah dilakukan sebagian besar orang-orang kaya itu untuk kemaslahatan umat manusia di planet ini? Adakah hal besar yang mereka karyakan?
Padahal jika kekayaan mereka disumbangsihkan untuk masa depan kemanusiaan, niscaya takkan ada cerita pilu macam di Afrika sana.
Sekarang mari kita amati apa yang terjadi dengan Sukarno, Dalai Lama, Gandhi, dan Mandela—sekadar menyebut beberapa nama.
Hingga tutup usia, Sukarno bahkan tak punya satu pun rumah untuk diwariskan pada anak-anaknya. Ia satu-satunya presiden termiskin papa—mungkin hingga saat ini.
Tapi ia mendirikan sebuah negara besar. Memerdekakan bangsanya, dan terlibat upaya kemerdekaan umat manusia sedunia dari penjajahan. Melawan ketidakadilan.
 Ilustrasi kesunyian
Ilustrasi kesunyianNah, ketidakadilan itulah yang kini mulai langka dalam dunia kita. Sepuluh persen manusia menguasai 90 persen kekayaan bumi. Sementara 90 persen sisanya, berebut sepuluh persen sisa kekayaan itu.
Tulisan ini belum lagi menyoal bagaimana prilaku kita terhadap alam. Banyak sekali manusia yang tak lagi bisa membangun hubungan mesra dengan alam yang ia tinggali.
Mereka tak peduli bahwa alam raya ini sejatinya juga organisme cerdas yang punya sistem kerjanya sendiri.
Tri Hita Karana
Dalam ajaran warisan luhur Nusantara, ada yang dikenal dengan sebutan Tri Hita Karana, yaitu: Tiga Penyebab Kesejahteraan (Parahyangan, Pawongan, Palemahan).
Parahyangan berarti, manusia mesti menjaga keharmonisan dengan Tuhan. Hal ini diejawantahkan melalui pemujaan, sesembahan/ibadah, bersyukur, nrimo ing pandum, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Ilahiyah atau agama.
Pawongan artinya, hendaklah manusia menjaga keselarasan antar sesama. Karena manusia merupakan mahluk sosial yang membutuhkan satu sama lain—melalui hubungan saling tenggang rasa dan komunikasi yang baik dalam komunitas masyarakat.
Palemahan adalah, setiap manusia harus menjaga keserasian dengan alam atau lingkungan hidup, termasuk alam gaib.
Di Yogyakarta, ketiga hal tersebut dituangkan ke dalam simbol garis imajiner simetris antara Gunung Merapi - Kerat(ua)on - Samudera Selatan (Parang Kusumo). Dalam diri kita menjadi: Akal, Hati, dan Tubuh.
Manusia berakal yang menggunakan hatinya dengan bijak, niscaya memiliki tubuh yang peka pada ruang-waktu.
Di mana pun ia berada, kesadaran pada waktu yang menghadirkannya di dunia, kelak mewujud sebuah kebajikan tiada ternilai bagi umat manusia yang lahir kemudian.
Pada ranah demikianlah keberadaan kita di bumi dipertanggungjawabkan. Jika kita terus melakukan pengabaian, maka kejatuhan umat manusia sedang menunggu di tubir jurang zaman.
Namun bila kita berhasil mendaki ke puncak kemanusiaan, di ranah itulah nirmala pengalaman kebertuhanan, menanti. Tuhan yang selama ini bathin bagi kita, dan kita dzahir bagi-Nya, melebur jadi Satu.
Pola seperti itulah yang mencerahkan para manusia adiluhung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.





















![[POPULER TREN] Manfaat Air Kelapa Muda Vs Kelapa Tua | Cara Perpanjang STNK jika Pemilik Asli Kendaraan Meninggal Dunia](https://asset.kompas.com/crops/FZBUBX2p8nktcjAzapmxt2q_pxE=/6x0:703x464/170x113/data/photo/2024/04/29/662fb4a7e31a9.jpg)




































