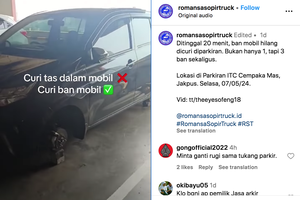"Bullying" dan Budaya Literasi
Terbayang bagaimana hancur dan tersayatnya jiwa orangtua si korban, yang berharap anaknya kembali dengan membawa ilmu pengetahuan, malah pulang sudah menjadi mayat dengan penuh luka dan lebam karena disiksa teman-temannya sendiri.
Peristiwa tersebut seolah sudah menjadi rutinitas tahunan, tetapi sampai hari ini belum ada penanganan serius dan komprehensif, mencari akar masalahnya dan bagaimana solusinya.
Bahaya sekali apabila bullying dianggap sebagai kenakalan remaja biasa, karena dampak dan efeknya bukan saja akan mencoreng dunia pendidikan, tetapi juga menjadi preseden buruk pada modal sosial bangsa Indonesia.
Tentu saja banyak faktor yang mengakibatkan perilaku bullying oleh peserta didik, di antaranya yang paling mendasar adalah buruknya ekosistem pendidikan, krisis keteladanan, dan kualitas serta kuantitas pengajar.
Dalam tulisan ini saya akan membahas faktor lain yang jarang dibahas, yaitu rendahnya budaya literasi peserta didik, yang menurut saya justru paling fundamental.
Bullying yang terjadi di sekolah dan pesantren elite seolah menegasikan peran infrastruktur. Kemegahan infrastruktur sekolah atau pesentren belum tentu menjadi jaminan kualitas pengajaran.
Namun mayoritas orangtua justru menjadikan kemegahan infrastruktur salah satu indikator kualitas lembaga pendidikan karena itulah yang kasat mata.
Biaya yang mahal juga seolah menjadi jaminan, karena sering kali dianalogikan dengan membeli barang, “harga tidak akan berdusta.”
Namun bullying juga sering terjadi di lembaga pendidikan yang infrastrukturnya sangat sederhana, bahkan seadanya. Namun, tidak bisa juga dijadikan pembenaran dengan anggapan bahwa yang megah saja seperti itu, apalagi yang kumuh.
Jadi potensi bullying atau kekerasan bisa terjadi dalam lingkungan apa saja, maka di sinilah pentingnya ekosistem yang bagus.
Peserta didik juga sangat sulit untuk mencari teladan di lingkungan terdekatnya. Ada peribahasa yang popular di masyarakat kita, “al-ummu madrasah al-ula, idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyiban al-a'raq.”
Artinya ibu adalah sekolah pertama, bila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi terbaik.
Dalam kenyataannya peran Ibu sebagai madrasah/sekolah bagi anak-anaknya kini sudah pudar. Ibu berperan hanya sebagai ATM saja.
Mereka banyak kehilangan sentuhan manusiawi yang tulus dari ibu dan bapaknya, para senior, dan para pengajar.
Mayoritas orangtua memercayai pendidikan anaknya 100 persen kepada sekolah atau pesantren. Entah karena tidak bisa, tidak peduli, atau karena kesibukan sehingga yang paling praktis dan pragmatis adalah menitipkannya di pesantren atau boarding school. Secara psikologis banyak murid atau santri menjadi yatim piatu.
Menarik sekali hasil riset yang dilakukan Litbang Kompas tentang gambaran pahlawan yang ternyata telah berubah di kalangan Milenial.
Relung imajinasi kaum Milenial lebih banyak dijejali sosok pahlawan super ketimbang pahlawan nasional. Idola kepahlawanan pembawa nilai-nilai tradisional seperti guru, pemuka agama, dan orang bijak telah tergeser oleh idola kepahlawanan pembawa nilai-nilai pasca-modern seperti artis, politisi populer. Idola lainnya adalah pahlawan dari dunia fiksi atau difiksikan. (Kompas, 5 November 2018).
Tantangannya adalah bagaimana supaya ruang imajinasi anak didik diisi dengan narasi tentang pahlawan yang paling dekat dengan dirinya seperti ibu dan ayah, guru, serta pahlawan nasional milik bangsa sendiri.
Pendekatan budaya literasi
Belakangan ini ada beberapa penelitian mengenai hubungan antara budaya literasi dengan tindakan kekerasan.
Dengan asumsi bahwa semakin tinggi budaya literasi di masyarakat, maka akan mengurangi tindakan kekerasan pada masyarakat itu, dan sebaliknya.
Misalnya, ada yang meneliti hubungan ini di sekolah dasar dengan kesimpulan bahwa semakin banyak seorang siswa membaca ternyata akan mengurangi, bahkan menghilangkan perilaku bullying.
Film populer "Freedom Writers" mengangkat kisah nyata tentang keberhasilan seorang guru dalam mengelola kelas dengan murid yang super bandel, bahkan kriminal, menjadi kelas yang penuh tolerasi, solidatiras, dan prestatif.
Untuk menaklukan kelas itu sang guru hanya menggunakan dua senjata, yaitu kisah dan buku atau budaya literasi.
Satu lagi tentang Malcolm X, seorang berandalan putus sekolah yang berhasil menjadi cendekiawan—dan akhirnya menjadi seorang politisi, bahkan dianggap sebagai pahlawan—di dalam penjara karena membaca.
Sebaliknya, orang yang kurang memiliki pengetahuan, akibat jarang atau tidak suka membaca, akan memiliki perilaku agresif atau melakukan kekerasan dalam merespons tantangan. Budaya literasi atau pengetahuan bisa dijadikan indikator perilaku.
Dalam artikelnya, mantan ketua PB NU K.H, Said Aqil Shiraj mengatakan bahwa para radikalis, jihadis, atau fundemantalis adalah orang-orang yang minim pengetahuannya.
Beliau menyodorkan solusi untuk deradikalisasi dengan pendekatan literasi, karena pendekatan yang selama ini digunakan tidak menyentuh ”isi kepala” dan tak sadar, malah mengabaikan potensi aktivisnya sebagai manusia yang suatu saat bisa berubah (Kompas, 8 Desember 2018).
Hasil pengamatan kami, sebagai fasilitator gerakan literasi nasional juga demikian: peserta didik yang tergabung dalam gerakan literasi sekolah memperlihatkan perilaku yang santun dan prestatif.
Bahkan ada murid SMP dan SMA yang memiliki pengetahuan lebih dewasa daripada umurnya—seperti mahasiswa semester akhir—karena dalam tantangan yang diberikan berhasil membaca buku sejumlah 149 judul dalam 10 bulan.
Dari berbagai penelitian dan pendapat para pakar ada indikasi bahwa siswa dan mahasiswa Indonesia, juga mayoritas penduduk, tidak terbiasa menganalisis informasi.
Fenomena hoax yang ramai sekarang ini adalah cermin bahwa masyarakat Indonesia belum bisa membedakan mana informasi yang benar dan palsu sehingga mudah ditipu atau diperdaya.
Membangun budaya literasi di lembaga-lembaga pendidikan adalah solusi tepat untuk mengeliminasi, bahkan menghilangkan perilaku bullying.
Gerakan literasi sekolah yang digulirkan oleh Kemendikbudristek sudah tepat, tetapi harus dilakukan revitalisasi dan pengembangan secara berkelanjutan, karena kelihatannya semakin hari semakin redup. (Tentang masalah ini lihat tulisan saya di Kompas.com dengan judul “Matinya Gerakan Literasi?”).
Namun harus diingat, kemahiran literasi saja bukanlah obat mujarab untuk mengobati bullying. Literasi hanyalah cara atau alat untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan.
Literasi seperti pisau bisa digunakan untuk menyembelih ayam atau menggorok leher manusia.
Dalam genggaman orang-orang pintar yang tidak bermoral, kemahiran literasi justru menjadi mesin kekerasan, bahkan mesin pembunuh yang paling berbahaya.
Oleh karena itu yang harus sangat diperhatikan adalah pesan atau isi dari bacaan, jangan sampai melupakan eksistensi Tuhan atau demensi moral dalam kegiatan membaca.
Nah, di sinilah kita melihat kembali pentingnya peran perpustakaan sekolah yang semakin hari semakin terpinggirkan.
Sejatinya, perpustakaan bisa dijadikan sebagai lokus gerakan literasi sekolah. Peran perpustakaan sebagai “jantung sekolah” tidak akan pernah bergeser, asalkan berada di tangan yang tepat sehingga bisa menjaga relevansi, tidak tergusur oleh kemajuan terknologi informasi, serta menjadi benteng moral sehingga tidak terjadi lagi bullying di sekolah dan pesantren.
https://www.kompas.com/edu/read/2024/03/10/100000271/-bullying-dan-budaya-literasi