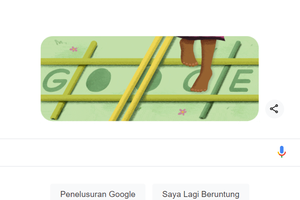Jangan Biarkan Tradisi dan Ritual di Mentawai Musnah

SEMINAR nasional di pedalaman Mentawai, di Desa Matotonan, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatra Barat, apakah relevan?
Meski hanya ada tujuh pemateri, seminar sehari yang menjadi bagian dari hajatan “Ulang Tahun Matotonan ke-42 dan Festival Lya Eeruk” pada tanggal 7-10 Agustus 2022 itu ternyata tidak hanya relevan tetapi juga membuka pikiran.
Masyarakat bersemangat datang ke aula balai desa, bahkan anak-anak sekolah, dan mereka tetap berada di tempat hingga akhir acara, mendengarkan orang-orang dari luar membicarakan desa mereka.
Beberapa di antara warga desa sengaja datang untuk memanfaatkan aliran listrik dari genset, buat mengisi baterai ponsel. Maklum, listrik di Matotonan hanya menyala pada pukul 18.00 hingga 00.00 tengah malam.
Baca juga: Jika UU 17/2022 Tidak Direvisi atau Dibatalkan, Masyarakat Mentawai Nyatakan Keluar dari Sumbar
Setelah itu, padam, hingga menyala lagi esok hari pukul 18.00. Jadi, warga hanya mendapatkan asupan listrik selama enam jam. Itulah mengapa malam hari menjadi acara kumpul keluarga untuk menonton siaran televisi, termasuk sinetron.
Seminar nasional bertema “Melestarikan Budaya Bumi Matotonan Menuju Desa Wisata Adat dan Religi yang Bermartabat dan Berdikari” yang digelar oleh Asosiasi Tradisi Lisan (ATL), Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatra Barat, dan Desa Matotonan tersebut menghadirkan pembicara para akademisi dan praktisi dari Padang, Jakarta, dan bahkan Kendari.
Mereka adalah Ketua Umum ATL Dr Pudentia MPSS; Ketua ATL Sulawesi Tenggara yang juga mantan rektor Universitas Halu Oleo Prof Dr Usman Rianse; Ketua Prodi Tradisi Lisan Universitas Halu Oleo Dr Rahmat Sewa Suraya; peneliti BRIN Dr Mu'jizah; pamong budaya ahli madya BPNB Sumbar Rois Leonard Arios S.Sos, M.si; pengusaha dan mantan Bupati Kepulauan Mentawai Dr (Cand) Yudas Sabagalebt, M.M; dan Kepala Desa Matotonan Ali Umran, S.H.
Beruntung wakil dari pemerintah kabupaten datang, yakni Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Nurdin S.Sos serta Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Mentawai Johny Anwar, sehingga berbagai masukan diharapkan dapat dibicarakan ke tingkat yang lebih tinggi dan mewujud dalam kebijakan serta program pelestarian budaya Mentawai.
Namanya juga harapan, bisa terkabul tapi bisa juga pupus jika tidak dikawal terus. Jangan sampai setelah datang seminar, menengok desa nun jauh, para pejabat itu lantas lupa.
Keistimewaan Mentawai
Mentawai. Nama itu tidak ditemukan di dalam arsip VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang pernah mengobrak-abrik Nusantara selama dua abad. Kepulauan Mentawai hampir tidak tersentuh, apalagi tereksploitasi.
Menurut sejarawan Mukhlis PaEni, sejumlah kata terkait Mentawai memang tertulis dalam arsip VOC, yakni Enggano, Mega, Sandung, Sibiru (Siberut), Nias, Nako, dan Pulau Banyak. Akan tetapi, Mentawai sama sekali tidak pernah disebut.
Kepulauan Mentawai baru "ditemukan" setelah tahun 1800 dalam arsip pemerintah Hindia Belanda. Di sana disebutkan bahwa Karesidenan Padangshe Benedenlanden juga meliputi Kepulauan Mentawai yang berstatus onderafdeling atau setingkat kecamatan.
Baru pada tahun 1999 Kepulauan Mentawai dengan empat pulau besar di dalamnya (Sipora, Sikakap, Pagai, dan Siberut) ditetapkan menjadi kabupaten.
Rupanya, VOC tidak dapat mengendus potensi komoditas pangan yang dapat diperdagangkan dan mendatangkan banyak cuan. Tidak ada apa-apa di Mentawai, berbeda dengan Madura dengan garamnya, Bangka dengan ladanya, atau Banda dengan palanya.
Meskipun demikian, di Mentawai terdapat banyak flora yang bermanfaat untuk pengobatan penyakit dan selama ini telah digunakan para sikerei (tabib/tokoh adat) untuk menyembuhkan warga yang sakit, mulai sakit panas, demam, batuk, kembung, pusing kepala, hingga cedera seperti terkilir, tersayat benda tajam, dan tersengat lebah.
Baca juga: 5 Kebudayaan Suku Mentawai, dari Tato hingga Tradisi Meruncingkan Gigi
Potensi pengobatan herbal tersebut rupanya tidak cukup menarik hati perusahaan Hindia Belanda. Tetumbuhan, yang beberapa di antaranya endemik, itu menjadi garapan para sikerei.
Kini, ketika pesona rempah-rempah mulai memudar (bukan karena tidak dibutuhkan, tetapi karena makin mudah didapatkan), para wisatawan mancanegara berbondong-bondong datang ke Mentawai demi alam dan budaya.
Selain mengincar pesona alam yang aduhai dan cocok untuk sekadar menyepi atau berselancar di lautnya, mereka juga mendokumentasikan beragam ritual yang dilakukan masyarakat, dipandu para sikerei. Lokalitas dan genuinitas menjadi pesona yang tidak lekang oleh waktu.
Pengalaman saya pada 6 Agustus 2022 di Pelabuhan Muaro Padang, saya menyaksikan belasan bahkan puluhan wisatawan mancanegara memasuki kapal cepat Mentawai Fast II.
Sejumlah turis menenteng papan seluncur, seperti lazim kita lihat di bandara Ngurah Rai Denpasar Bali.












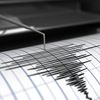
























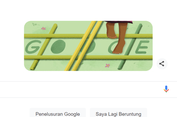





![[POPULER TREN] Dampak La Nina bagi Indonesia | Beberapa Makanan Mengandung MIkroplastik](https://asset.kompas.com/crops/v1Nk-5jwH6KNXVD-XqJ_53_SeoE=/11x0:790x519/177x117/data/photo/2024/04/28/662e6cfd33f9c.jpg)








![[POPULER MONEY] Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen | Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai](https://asset.kompas.com/crops/QahF4sKlvT-3_0hPRMQBd7lz0IA=/0x0:1000x667/300x200/data/photo/2023/11/28/6565a1f461721.jpg)