
Sastra sebagai Panggung Anarkisme

MENARIK bahwa minat akan karya sastra semakin tumbuh dan berkembang dengan pesat di Indonesia bertepatan dengan peringatan 100 tahun Chairil Anwar pada tahun ini. Hal itu diperlihatkan melalui berbagai sayembara, lomba, dan publikasi karya sastra yang kerap diselenggarakan dan diikuti berbagai kalangan. Itu artinya, karya sastra sama sekali tidak pernah mangkir atau menghilang dari kehidupan sehari-sehari, baik secara akademis, kulturalis, maupun politis.
Boleh jadi memang ruang untuk karya sastra beralih rupa. Dengan semakin terdesaknya media cetak dan semakin populernya media digital, ruang untuk berekspresi, apalagi berinteraksi, tentu semakin terbatas akibat tuntutan dari kemajuan teknologi dan informasi di masa kini. Dengan kata lain, media digital tampak semakin merajalela dan berkuasa, sedangkan media cetak semakin terpinggir dan tersingkirkan.
Baca juga: Kontroversi Karya Sastra Angkatan 66
Hal itu mengakibatkan ruang untuk berdialog secara publik dan tercetak, khususnya dalam konteks karya sastra, menjadi semakin terkucilkan, meski masih tetap mampu menyintas di ruang-ruang digital secara privat dan tanpa publisitas, seperti Facebook, Instagram atau Twitter.
Sarana perjuangan antikolonial
Penyintasan karya sastra di ruang-ruang seperti itu telah memprivatisasi daya dan kuasa imajinasi dari berbagai karya sastra yang sesungguhnya berperan sebagai panggung bagi "komunitas-komunitas terbayang" (imagined communities). Benedict Anderson dalam bukunya yang berjudul Imagined Communities atau Komunitas-komunitas Terbayang (Yogyakarta: Insist & Pustaka Pelajar, 2001), menjelaskan bahwa karya sastra, seperti novel, cerpen atau puisi, berperan amat penting dalam menggerakkan perjuangan antikolonial.
Hal itu karena karya-karya tersebut telah membantu dan memberi cerita tentang cita-cita untuk menjadi negara bangsa yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Jadi, berkat cerita-cerita dari berbagai karya sastra itu, para nasionalis awal yang berjuang untuk lahirnya Indonesia, misalnya, dapat menghasilkan beragam pembayangan mengenai gagasan kebangsaan (nasionalisme) yang antikolonial.
Itulah mengapa Mas Marco Kartodikromo atau Pramoedya Ananta Toer selalu berhadapan dengan para penguasa yang amat berambisi untuk membangun koloni-koloni demi semakin memperkokoh daya cengkeram kekuasaannya. Akibatnya, mereka pun harus keluar masuk bui atau penjara, bahkan berisiko dibuang atau diasingkan.
Dalam konteks ini, karya sastra berintensi dan bertendensi untuk selalu mengungkap perjuangan dari masyarakat yang tidak dapat bersuara dengan lantang dan memaknainya demi mengobarkan semangat perlawanan dari masa ke masa. Sebab dengan perubahan zaman yang semakin cepat dan serba tak terduga ini, perlawanan terhadap para pemburu kekuasaan yang semakin mengglobal tetap perlu dikerjakan agar tidak mudah terlena oleh bujuk rayu ideologi beraroma pascakolonial, atau bahkan pascakebenaran.
Maka menjadi penting untuk selalu diingat dan dicatat bahwa karya sastra sepanjang zaman sebenarnya adalah panggung dari perlawanan global yang dalam kajian lain dari Anderson dinamai anarkisme.
Dapat menyemai benih perlawanan
Dalam bukunya yang berjudul Di Bawah Tiga Bendera: Anarkisme Global dan Perlawanan Antikolonial (Serpong, Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2015), Anderson memperlihatkan hal itu melalui perjuangan Jose Rizal di Filipina yang pada mulanya membangun basis perlawanannya melalui karya-karya sastranya. Pertama, dengan novel Rizal yang berjudul Noli Me Tangere (Jangan Sentuh Aku). Kedua, dalam novel yang berjudul El Filibuterismo (Merajalelanya Keserakahan).
Melalui kedua novel itu, Rizal mampu menyediakan sebuah cara pandang dalam bentuk "teleskop terbalik" (spectre of comparisons) bagi para pembacanya. Dengan teleskop itulah, pemandangan dari kenyataan hidup sehari-hari di sebuah negara kolonial seperti Filipina menjadi sedemikian kontras.
Baca juga: 8 Jenis Karya Sastra serta Penjelasannya
Kontrasnya, seperti memandang dari balik kaca pada kabin pesawat atau gerbong kereta api di mana segalanya menjadi tampak indah dan menyenangkan di depan mata. Namun sesungguhnya ada banyak pemandangan yang mengenaskan saat turun dari pesawat atau kereta api lantaran di sana tampak dengan jelas dan tajam, kehidupan masyarakat yang miskin, tersingkir, dan terbuang. Hal itu telah dibahas dengan jeli dalam buku Anderson yang berjudul Hantu Komparasi: Nasionalisme, Asia Tenggara, dan Dunia (Yogyakarta: Qalam, 1998) yang mampu menyediakan cara pandang yang unik atau khas terhadap realitas hidup sehari-hari.
Cara pandang seperti itu yang mampu membongkar panorama dan gaya hidup kolonial dan/atau global adalah sebuah bahasa perlawanan yang perlu direpresentasikan melalui karya sastra. Sebab dengan bahasa yang mampu meretakkan, apalagi memporak-porandakan, segala sesuatu yang tampak rapi dan teratur seperti susunan batu bata dari sebuah tembok pada bangunan dapat ditunjukkan apa yang tampak retak dan berpotensi untuk dijadikan celah perlawanan.
Sama seperti jalan beraspal yang terasa halus dan mulus untuk dilalui mobil, misalnya, tetap dapat berisiko menimbulkan terjadinya kecelakaan akibat adanya bolong-bolong di jalanan. Itulah bahasa yang perlu ditampakkan dalam karya sastra sebagai daya dan kuasa perlawanan terhadap segala bentuk kolonialisme.
Tentu, tetap perlu diwaspadai bahwa karya sastra ibarat penyambung lidah dari para sastrawan yang menyampaikan dering peringatan kritis demi semakin berkobarnya api perlawanan. Karena itulah, karya sastra mesti dapat mengambil peran di atas panggung sebagai intelektual publik (Benedict Anderson, “Few Intellectuals in Court of Public Opinion”, Bangkok Post, June 28, 2010).
Itu artinya, peran yang dimainkan lebih sebagai seorang "pawang singa" (lion tamer) daripada sekadar "peniup seruling" bagi ular (snake charmer). Peran yang tidak mudah untuk dipentaskan, tetapi cukup efektif dan operatif sebagai daya dan kuasa untuk membangun perlawanan dari bawah. Perlawanan yang rela untuk berkorban demi sesama daripada mengorbankan nyawa orang lain sebagaimana telah diperankan oleh para sastrawan selama ini.
Di sinilah karya sastra dapat menjadi wahana untuk menyemai benih-benih perlawanan terhadap kekuasaan yang semata-mata hanya melayani kemegahan demi kepentingan sesaat dan sepihak belaka (Clifford Geertz, Negara Teater: Kerajaan-kerajaan di Bali Abad Kesembilanbelas, Yogyakarta: Bentang, 1980).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.




















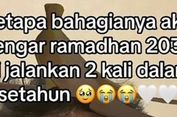













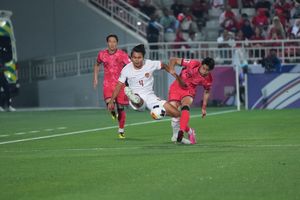











![[POPULER TREN] Sejarah Hari Ayah Sedunia | Penjelasan PLN soal Denda Segel Meteran Rp 68 Juta](https://asset.kompas.com/crops/ZLV-jEonLi8zZ1yx31N5NXUGE1w=/282x114:1229x746/95x95/data/photo/2022/06/20/62afb3efd7561.jpg)





