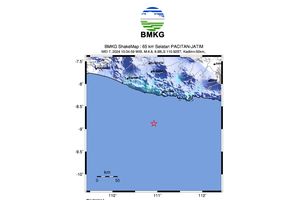Branding Cara Baru, Bukan Monopoli Marketer
Banyak orang yang bekerja di bidang marketing dan branding berpikir bahwa membangun merek bisa dilakukan dengan cara menciptakan cerita bagus tentang merek terkait.
Meminjam perkataan Marc Mathieu, marketing awalnya adalah tentang menciptakan mitos. Branding apa pun bentuknya, banyak diperlakukan seperti adu bagus bikin cerita layaknya film fantasi ala Disney.
Lihatlah narasi dan citra yang dibuat berbagai merek demikian indahnya. Kita pun sejenak dibawa ke “dunia fantasi”.
Lihat pula bagaimana para pemimpin perusahaan memilih dan menetapkan nilai perusahaan yang berisi kata-kata indah; teamwork, innovation, can do attitude dan lain sebagainya.
Permasalahannya, sering kali cerita tersebut berakhir sebatas takhayul karena tidak pernah terjadi.
Membuat janji-janji indah adalah satu hal, namun memenuhinya adalah hal lain yang justru tidak kalah penting.
Era branding melalui mitos ini diterima cukup lama karena konsumen hidup tanpa akses media.
Sehingga satu-satunya yang bisa membentuk opini dan persepsi hanyalah pemilik merek yang notabene memiliki modal besar untuk membeli “perhatian” publik melalui media.
Sementara sebagai konsumen yang tidak punya akses terhadap media, kita hanya bisa menjadi penerima pasif.
Jika citra bentukan merek dipercaya maka kita pun mengamini, jika tidak sejalan ya sudah tidak usah dipermasalahkan dan dipakai.
Tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh konsumen untuk menyikapinya secara lebih aktif.
Mitos yang kemudian menjadi takhayul karena tidak terbukti realitanya ini tidak lantas gugur.
Karena realita kualitas produk yang baik seperti digambarkan dalam narasi merek tidak selalu bisa diukur, mengingat tidak semua produk memiliki tangible parameter terhadap kualitasnya.
Krim pemutih sulit diukur secara instan hanya dari satu dua pemakaian, pasta gigi pun sulit untuk dibuktikan keampuhannya dalam membersihkan gigi dan membunuh kuman.
Akhirnya justru mitos-mitos bentukan merek inilah yang memberikan sugesti konsumen tentang hasilnya tersebut ketimbang realitanya sendiri.
Yang membuat kita merasa pasta gigi cukup ampuh untuk membersihkan gigi dan membunuh kuman pada akhirnya adalah cerita bentukan merek itu sendiri ketimbang produknya.
Tidak heran Pepsi Challenge yang sejak tahun 1970 melalui serangkaian blind test membuktikan bahwa produk mereka lebih terasa nikmat dan digemari banyak orang ketimbang Coca-Cola pada akhirnya justru terpuruk.
Berbagai percobaan ilmiah pun membuktikan bahwa kualitas rasa sebuah makanan yang terbentuk di otak tidak bisa dilepaskan dari pengaruh banyak hal, mulai dari tampilan, harga, dan juga merek dari restoran yang menjualnya.
Ketika kita makan makanan mahal di restoran terkenal secara bawah sadar otak kita membawa sugesti diri kita bahwa ini adalah makanan enak.
Dan sugesti ini berkontribusi terhadap bagaimana otak kita mengukur kualitas rasa makanan tersebut.
Imagery, cerita-cerita indah dan setiap detail dari brand storytelling yang dibuat oleh merek-merek pendongeng ini pun sering kali menciptakan bikeshedding effect.
Ini adalah bias yang membuat kita terfokus pada hal yang tidak penting dan mengabaikan hal yang penting.
Bikeshedding effect adalah fenomena di mana kita berfokus pada sosok artis yang terkenal dalam sebuah iklan, ceritanya yang bagus, dan berbagai detail yang sebenarnya tidak berkontribusi atau berhubungan pada bagaimana kualitas produk dari merek yang memiliki narasi baik tadi.
Restoran yang instagramable sering kali digemari bahkan ketika kualitas rasa makanannya biasa-biasa saja. Orang lebih fokus pada interiornya yang cantik dibanding rasa makanannya.
Dalam tahap selanjutnya narasi dan citra indah dari merek juga bisa mendorong bandwagon effect, yaitu tendensi untuk mengikuti apa yang sepertinya disukai oleh orang lain di sekeliling kita.
Kita berpikir kalau orang-orang rela antre untuk mendapatkannya ini pasti produk yang baik.
Kita tidak berpikir bahwa orang-orang yang sedang mengantre itu bisa juga melakukannya karena orang lain yang lebih dulu dari mereka mengantre.
Hal ini terus bergulir hingga akhirnya konsumen benar-benar “kehilangan akal” nya dan mulai terkena placebo effect, yaitu sugesti diri yang berdampak nyata pada diri kita bahkan ketika tidak ada kontribusi fisik dari produknya.
Ketika semua ini terjadi, maka fungsi branding banyak didominasi oleh fungsi-fungsi marketing dalam menciptakan cerita, membangun narasi dan menciptakan imajinasi menjadi lepas dari realitasnya terhadap merek.
Risiko mendapat penentangan dari konsumen menjadi amat minim, karena toh konsumen tidak punya kekuatan untuk bersuara.
Marc Mathieu dalam kutipan di awal tulisan juga mengatakan bahwa saat ini marketing (branding) adalah tentang menyebarkan realita.
Mewabahnya media sosial menyediakan akses bagi konsumen untuk juga bisa bersuara. Dan tidak jarang akses ini juga digunakan untuk menyuarakan persetujuan atas narasi yang sejalan maupun disonansi dari narasi merek yang tidak sesuai realita.
Ketika narasi merek sesuai realita maka konsumen tidak sungkan untuk ikut mengambil peran sebagai brand ambassador dengan menyebarkannya.
Sebaliknya, ketika narasinya hanya janji-janji surga yang jauh dari kenyataan maka mereka tidak akan segan-segan menghukum dengan cara membuka aibnya ke jaringan mereka.
Kehadiran akun meme di media sosial seperti hrdbacot, ecommurz, ridehaluing adalah bentuk kontrol para pekerja digital terhadap perusahaan yang rajin bermimpi namun malas untuk membuat mimpinya menjadi kenyataan.
Branding bukan lagi tentang storymaking competition tapi berubah menjadi narasi yang selaras dengan realitanya.
Seolah-olah sebegitu lelahnya konsumen dengan cerita indah yang jauh dari realita membuat konten-konten yang beredar di media lebih memprioritaskan orisinalitas ketimbang kecantikan.
Video-video yang secara sinematografi bisa dibilang jauh dari indah dan cantik ternyata bisa menjaring jutaan “mata” dan “jempol” ketika mempertontonkan hal menarik yang orisinal.
Walaupun narasi tetap penting karena bisa membawa kita berandai-andai, namun tanpa realita maka rasanya seperti sedang dighosting gebetan, berharap tanpa tahu kapan akan jadi kenyataan.
Pada akhirnya branding adalah tentang pengalaman yang indah sesuai narasi. Konsekuensinya, semua yang memiliki andil terhadap penciptaan pengalaman ini baiknya mengerti branding.
Ini dimulai dari petinggi perusahaan, perencana produk, tenaga penjual, frontliner, dan sudah pasti pekerja marketing.
Pengalaman yang berpengaruh terhadap branding di sini punya banyak dimensi, bukan hanya terbatas pada kualitas produk/layanan saja, tapi juga pengalaman yang memiliki rasa.
Mengambil pelajaran dari merek-merek besar dunia yang sudah memupuk fondasi kuat di zaman konsumen memiliki kontrol dan akses yang terbatas pada media, mereka bertahan karena sudah menerapkan branding yang selaras antara narasi dan realita.
Apple dan Nike misalnya, produknya unggul (kalau tidak bisa dibilang paling baik), selaras dengan narasinya.
Dan yang paling penting brand belief dan karakter yang memiliki rasa. Dan ini hanya bisa terjadi ketika cetak biru merek diturunkan dari atas secara konsisten ke setiap bagian dalam perusahaan sehingga selaras antara belief, narasi dan realitanya.
Apple dan Nike bisa menjadi merek besar bukan hanya karena tim marketingnya, namun karena Steve Jobs dan Phil Knight mengerti merek.
Mereka benar-benar memberikan arahan yang jujur dan otentik yang kemudian menjadi nafas perusahaan dan roh dari apa pun yang dilakukan setiap bagian dalam perusahaan.
Menciptakan merek besar bukanlah sekadar menciptakan narasi, menciptakan merek besar juga tidak cukup dilakukan dengan menciptakan produk dan layanan yang baik saja.
Berulang kali dalam hidup, kita membuktikan bahwa sesuatu yang terbaik belum tentu menjadi yang paling sesuai untuk kita.
Experience bukanlah tentang interaksi yang didasarkan perhitungan matematis untung-rugi, baik-buruk, namun juga mengenai memiliki rasa yang unik dan tidak bisa dibandingkan.
Merek pun harus membangun rasa yang unik dan “ngangeni” melebihi obsesi menjadi yang terbaik.
Hati kita memiliki kekuatan lebih besar dari otak kita maka dari itu ketika rasa sudah bicara, maka baik-buruk tidak lagi jadi masalah, kita siap menerima dia apa adanya.
Dalam buku Brain & Brand, saya memperkenalkan konsep hirarki merek yang mengedepankan konsep merek dalam tingkatannya.
Teori ini memperkenalkan konsep pentingnya untuk membangun love beyond logic. Ini adalah konsep di mana merek tidak sekadar bermain dalam taraf familiarity seperti dilakukan merek-merek pendongeng sebelum media sosial muncul.
Merek juga tidak boleh cepat puas pada tahap resonate yang mengedepankan kualitas produk semata.
Merek setidaknya harus berada di tahap inspirasi, dicintai karena belief, karakter, personalitas, dan prinsipnya.
Dan walaupun kualitas produk dan layanan tetap penting, namun tidak menjadi panglima utama dalam membangun merek, melainkan hanya pendukung.
Kesimpulannya, kehadiran media sosial memberikan akses kepada konsumen untuk juga bersuara, sehingga branding bukan lagi jadi monopoli orang-orang marketing.
Branding merupakan upaya kolektif yang terintegrasi dari setiap orang di perusahaan yang harus dipimpin oleh pimpinan perusahaan.
Branding bukan lagi tentang adu dongeng tapi juga tentang mewujudkan dongengnya dalam kenyataan, kualitas produk dan layanan dan juga membangun rasa yang unik.
Dan pada akhirnya walaupun pengalaman dibentuk di toko/outlet, namun karena merek dibentuk di benak konsumen, maka kemampuan untuk mengerti bagaimana otak merekonstruksi merek di benak mereka menjadi satu kewajiban.
Agar kita bisa menyelaraskan narasi, realita dan rasa.
https://www.kompas.com/properti/read/2021/03/29/130000821/branding-cara-baru-bukan-monopoli-marketer