Kekuasaan dan Harapan Terwujudnya Keadilan Sosial
KEKUASAAN itu amat memesona. Orang bahkan rela menderita atau bahkan menyakiti sesama manusia demi kekuasaan.
Bagaimana tidak, dengan memegang kekuasaan seseorang bukan saja memiliki privilege terhadap yang dikuasainya, tetapi juga memungkinkan si empunya menciptakan sejarah yang berpengaruh dalam kehidupan banyak orang.
Sejarah perjalanan bangsa, peralihan rezim kekuasaan, khususnya di era pasca-kemerdekaan, identik dengan kekerasan yang diikuti instabilitas sosial, ekonomi, dan politik.
Peralihan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru diwarnai dengan penumpasan G30SPKI yang memakan jutaan korban rakyat Indonesia. Begitu juga peralihan rezim Orde Baru ke era reformasi juga diwarnai dengan kekerasan yang juga memakan korban jiwa.
Di era reformasi yang seharusnya hadir untuk merayakan kebebasan dari belenggu kepemimpinan otoriter yang bertahan selama 32 tahun, penegasan identitas budaya dan isu mayoritas-minoritas yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa justru kerap dipolitisasi oleh kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan.
Lalu apa itu kekuasaan dan mengapa manusia begitu terobsesi pada kekuasaan?
Apa itu kekuasaan?
Filsuf asal Jerman Friedrich Nietzsche mengatakan bahwa pada dasarnya manusia tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan karena keinginan untuk berkuasa ada pada tiap individu.
Hasrat akan kekuasaan (the will to power) merupakan naluri tirani manusia yang memungkinan manusia melakukan apa saja untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan sekalipun harus dengan menyingkirkan orang atau kelompok lainnya yang dianggap mengancam keberadaannya.
Selain penumpasan terhadap simpatisan PKI di era Orde Baru, kita tentu masih ingat dengan operasi penembak misterius (petrus) yang tidak lain adalah strategi pemerintah zaman itu untuk mempertahankan kekuasaan dengan membuat masyarakat bergantung dan patuh pada negara dan militer.
Senada dengan Nietzsche, filsuf anti-finalis asal Perancis, Michel Focault menjelaskan bahwa bentuk kekuasaan mengalami transformasi secara evolutif sejalan dengan perkembangan jaman.
Jika dulu kekuasaan selalu identik dengan kekerasan, represi (Freud, Rich), pertarungan kekuatan (Machiavelli), atau dominasi kelas yang dikaitan dengan penguasaan atas ekonomi dan manipulasi ideologi (Marx), kekuasaan di era modern lebih bersifat produktif dan tersebar.
Bagi Foucault, kekuasaan ada dalam tiap relasi sosial, tersebar, dan beroperasi dalam bentuk manajemen: manajemen energi, kemampuan, dan kehidupan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari ilmu pengetahuan (power/ knowledge).
Ilmu pengetahuan yang memanfaatkan bahasa sebagai alat untuk mengartikulasikan kekuasaan menjadi alat dominasi andalan yang meminimalisasi kekerasan fisik dan menyulapnya menjadi dominasi simbolik.
Contohnya, relasi sosial antara dokter dan pasien. Dokter yang notabene memiliki pengetahuan tentang medis memiliki kekuasaan atas pasiennya. Kemudian tes wawancara mengekslusi individu yang tidak masuk ke dalam kriteria ‘ideal’ calon pegawai. Demikian juga kriteria kecantikan tertentu yang melahirkan wacana bentuk tubuh “ideal” dan hidup sehat.
Artinya, bentuk-bentuk kekuasaan hegemonik yang ditopang oleh pengetahuanlah yang diandalkan oleh individu maupun kelompok di era modern untuk memantapkan kekuasaan dengan bentuk pendisiplinan (disciplinary power) yang membuat orang secara sukarela “menormalisasi” diri untuk menjadi “ideal”.
Namun, bagi Foucault kekuasaan tidak selalu diartikan secara negatif karena kekuasaan juga bisa bersifat positif seperti seorang dosen yang memiliki pengetahuan akan bidang tertentu yang membantu mahasiswanya untuk meraih gelar sarjana, atau orangtua yang memiliki kuasa terhadap anaknya untuk mengajarkan prinsip dan nilai kesopanan.
Artinya, untuk mewujudkan atau menciptakan realitas sosial yang "ideal" dan adil kita juga memerlukan kekuasaan.
Foucault juga menjelaskan bahwa bentuk kekuasaan dalam masyarakat modern mengandalkan wacana pengetahuan karena penguasa membentuk wacana tertentu untuk mempengaruhi pandangan masyarakat tentang suatu realitas tertentu.
Kekuasaan dan budaya politik di Indonesia
Beberapa tahun terakhir, pertarungan kelompok elit politik dalam memperebutkan kekuasaan masih terbilang memprihatinkan. Bagaimana tidak, maraknya black campaign berbasis SARA, politik dinasti, dan pencederaan terhadap demokrasi masih banyak ditemukan dalam panggung perpolitikan negeri ini.
Misalnya, dalam pilpres 2019 kemarin, isu-isu SARA, ujaran kebencian, disinformasi, serta saling lempar olok-olok yang tidak substantif dikapitalisasi untuk mendukung masing-masing calon pemimpin demi memperebutkan kekuasaan.
Kondisi ini juga diperparah dengan maraknya penyebaran konten-konten negatif yang tidak mendidik dengan memobilisasi influencer dan buzzers. Hal ini tentunya membuat pemilu menjadi tidak berkualitas.
Demokrasi disalahartikan menjadi kebebasan berpendapat yang mengabaikan nilai-nilai kesopanan dan kualitas diri sehingga hal ini berakibat pada polarisasi masyarakat ke dalam sekat-sekat sosial yang berpotensi memecah persatuan nasional.
Pesta demokrasi yang seharusnya secara substantif bertujuan untuk memilih pemimpin yang ideal, adil, dan mengabdi kepada masyarakat dan negara berubah menjadi perebutan kekuasaan semata.
Refleksi diri dan kekuasaan
Secara kritis kita harus menyadari bahwa kekuasaan tertentu selalu melahirkan anti-kekuasaan atau penolakan sehingga hal ini bisa menjadi refleksi kita bahwa realitas itu beragam.
Oleh karena itu, kita juga harus paham bahwa penolakan dan perlawanan harus masuk dalam pertimbangan strategis dan merupakan bagian dari proses demokrasi yang tidak dapat kita pungkiri.
Dengan kata lain kita harus mengakui dan merangkul realitas ini untuk memahami bahwa demokrasi adalah proses belajar yang panjang.
Bertolak dari pemikiran Foucault bahwa kekuasaan juga dapat bersifat positif, secara reflektif kita seharusnya lebih bijak dalam menggunakan kekuasaan.
Pemahaman kita terhadap konsep kekuasaan ini seharusnya menjadi refleksi diri baik untuk pribadi maupun kolektif supaya tidak bersikap sewenang-wenang terhadap sesama manusia.
Melalui pemahaman ini pemegang kekuasaan juga diingatkan akan tanggung jawab etis dan moral karena pemegang kekuasaan merupakan figur sentral yang memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan menjaga keharmonisan di masyarakat.
Pengalaman politik dalam pilkada dan pemilu kemarin yang diwarnai dengan berbagai hal negatif seharusnya bisa dijadikan pembelajaran berharga untuk kedewasaan politik negeri ini di masa yang akan datang, bahwa dalam memilih seorang pemimpin kita harus mengedepankan budaya demokrasi dan sikap selektif.
Hal ini kita lakukan untuk mendapatkan pemimpin ideal yang bertanggung jawab, adil, dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang demi kepentingan pribadi maupun golongan.
https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/21/075101365/kekuasaan-dan-harapan-terwujudnya-keadilan-sosial




















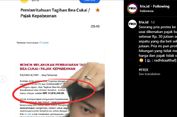





![[POPULER TREN] Jalan Kaki untuk Menurunkan Berat Badan | Kenaikan UKT Unsoed](https://asset.kompas.com/crops/3GPiBLU2-8lFy7pk6p6Qqa_fJYo=/0x200:834x756/177x117/data/photo/2024/04/26/662ad7bad0287.jpeg)















