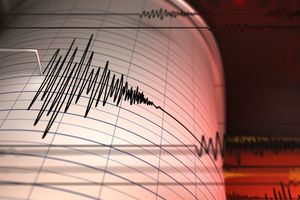Saat Emoji "Thumbs Up" Diakui sebagai Persetujuan Kontrak oleh Pengadilan
Pengadilan Kanada membuat putusan mengakui emoji “thumbs-up” sebagai tindakan hukum penerimaan dan persetujuan kontrak.
Sebagaimana dilansir The New York Times dalam rilisnya berjudul Canadian Court Rules Emoji Counts as a Contract Agreement (7/7/2023), Pengadilan Kanada mengakui emoji “thumbs-up” sebagai bukti kesepakatan kontrak.
Dalam putusannya, hakim menyebut sebagai realitas baru dalam masyarakat Kanada yang harus dihadapi oleh pengadilan.
Tulisan ini adalah bahan ajar saya tentang Hukum E-commerce di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Materi ini saya bagikan juga kepada pembaca Kompas.com untuk manfaat lebih luas.
Putusan pengadilan
Kasus ini terjadi saat seorang petani di Saskatchewan bernama Chris Achter bermaksud menjual 87 metrik ton rami kepada seorang pembeli bernama Kent Mickleborough pada 2021.
Pembeli kemudian menandatangani kontrak dan mengirimkan fotonya secara online kepada Chris Achter, yang kemudian dibalas dengan emoji jempol ke atas atau thumbs-up.
New York Times lebih lanjut melaporkan bahwa di persidangan Chris Achter menyatakan bahwa emoji thumbs-up hanya menegaskan bahwa ia menerima kontrak dan bukan konfirmasi telah menyetujui ketentuan.
Setelah memahami teks tersebut, maka kontrak lengkap akan dilanjutkan melalui faks atau email untuk dipelajari dan ditandatangani.
Kent Mickleborough, sebaliknya menunjukkan bahwa ketika ia mengirim foto kontrak tersebut ke ponsel Chris Achter, ia menulis, “tolong konfirmasi kontrak rami” dan dijawab Chris Achter dengan emoji jempol, yang diartikannya sebagai persetujuan kontrak tersebut.
Dalam persidangan, hakim mencatat bahwa Chris Achter dan Kent Mickleborough memiliki hubungan bisnis yang sudah berlangsung lama, seringkali mengirim pesan online tentang kontrak dan dijawab dengan mengirim pesan singkat.
Hakim TJ Keene menyatakan bahwa kedua belah pihak dengan jelas memahami bahwa tanggapan singkat ini dimaksudkan sebagai konfirmasi kontrak. Dengan demikian, bukan sekadar pengakuan telah diterimanya naskah kontrak.
Hakim Keene memutuskan terdapat kontrak yang sah antara para pihak. Hakim juga menyatakan Chris Achter telah melanggar kontrak tersebut karena tidak mengirimkan rami.
Hakim menghukum Achter membayar ganti rugi sebesar 82.200 dollar Kanada, atau sekitar 61.000 dollar AS karena wanprestasi akibat kontrak "thumbs up" itu.
Profesor Laura E. Little, dari Temple University Beasley School of Law, menyebut keputusan tersebut sebagai hal luar biasa dalam dunia komunikasi baru ketika emoji dapat mengatasi jebakan pembuatan kontrak.
Sementara pengacara Chris, Jean-Pierre Jordaan, memperingatkan bahwa mengakui emoji jempol sebagai bentuk hukum persetujuan kontrak akan “membuka pintu air” untuk segala macam kasus yang meminta pengadilan untuk mendefinisikan arti emoji lain, seperti jabat tangan atau tinju.
Profesor Julian Nyarko, dari Stanford Law School, mengatakan, ujian hukum untuk persetujuan kontrak berpusat pada bagaimana orang yang berakal sehat akan menafsirkan tanda-tanda yang diberikan kedua belah pihak. Ia menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, persetujuan lisan saja sudah cukup.
Belajar dari kasus ini, kita perlu mengingatkan hakim dan penegak hukum untuk tidak mengeneralisasi tafsir atas emoji dan emoticon. Penggunaan fitur ini dalam perbuatan hukum harus ditafsirkan secara cermat sesuai latar belakang dan fakta-fakta yang menyertainya.
Penegak hukum harus mempersempit ruang tafsir dan lebih fokus melihat unsur niat pengirim dan maksud penerima, keadaan sekitar, teks yang menyertainya, serta kebiasaan dan fakta sebelumnya yang menyertai kasus itu.
Hal yang perlu diingat bahwa pemaknaan simbol seringkali tidak universal. Seperti diungkanpan Heather King dalam publikasi pada media American Bar Association (ABA) (1/1/2022), bahwa layaknya tindakan fisik tertentu, makna simbol juga berbeda-beda.
Emoji “jempol ke atas” dianggap menyinggung atau vulgar di banyak negara. Emoji “wajah tersenyum” sering dianggap sebagai ekspresi sarkasme di negara lainnya. Sementara, keduanya sering dianggap sebagai ekspresi positif di sebagian besar negara lain.
Heather King menyatakan, selain rumitnya penafsiran makna emoji di pengadilan, terdapat pula permasalahan platform pesaing seperti antara Apple, Samsung dan lainnya.
Meskipun Konsorsium Unicode menetapkan standar untuk emoji, tetapi masing-masing perusahaan merancang platform mereka sendiri di mana platform unik ini terkadang menimbulkan inkonsistensi dan miskomunikasi karena pengirim dan penerima menggunakan platform digital berbeda.
Heather King juga mencontohkan kasus lain di Ohio, State v. Disabato. Seorang terdakwa dihukum karena pelecehan online setelah mengirimkan pesan teks yang tidak diinginkan, dan beberapa di antaranya menyertakan emoji tikus atau hewan pengerat yang sering digunakan sebagai eufemisme untuk seseorang yang tidak setia.
Lex informatica dan Hukum Transformatif
Secara konservatif hukum biasanya bersumber dari perilaku sosial, realitas kultural dan kebiasaan-kebiasaan manusia dan komunitasnya. Hal-hal ini kemudian dipercaya sebagai sumber pembentukan hukum.
Di negara Common Law, hukum itu diwujudkan melalui putusan pengadilan sebagai yurispridensi. Sedangkan di negara-negara berbasis Eropa Kontinental atau Civil Law diwujudkan dalam bentuk regulasi tertulis berupa perundang-undangan.
Saat ini terdapat perkembangan sangat signifikan. Di mana dalam lingkungan platform digital dan jaringan masyarakat informasi, regulasi bukanlah satu-satunya sumber hukum.
Kemampuan teknologi dan pilihan desain sistem dan fitur-fitur digital seringkali berlaku sebagai kebiasaan yang dianggap sebagai hukum bagi komunitas penggunanya.
Prinsip Lex informatica dikemukakan di antaranya oleh Profesor Joel R Reidenberg dari Fakultas Hukum Fordham University.
Pembuatan dan implementasi kebijakan informasi tertanam dalam desain, dan standar jaringan serta konfigurasi sistem. Bahkan preferensi pengguna dan pilihan teknis, menciptakan aturan kebiasaan yang biasanya diikuti.
Seperangkat kebiasaan dalam platform digital, arus informasi yang diciptakan teknologi, dan jaringan komunikasi, kemudian membentuk “Lex Informatica”.
Realitas ini tentu harus dipahami, diakui, dan dijadikan norma cyber law oleh para pembuat kebijakan dengan selektif dan tidak digeneralisasi.
Frasa "harus selektif" sengaja saya tekankan, karena berbagai kebiasaan dan "digital norm" itu bisa jadi tidak seluruhnya positif. Banyak juga yang mengandung unsur negatif, bahkan mengancam keselamatan umat manusia.
Pentingnya selektifitas ini antara lain, misalnya, untuk regulasi bidang Artificial Intelligence (AI) yang menjadi perhatian semua negara saat ini.
Emoji adalah contoh kebiasaan digital yang memiliki fungsi ungkapan faktual. Banyaknya kasus penggunaan emoji membuat sistem hukum lex informatica harus bekerja.
Untuk negara-negara Common law bisa jauh lebih responsif karena hukumnya ditetapkan melalui case law dan yurisprudensi.
Sedangkan untuk negara-negara Eropa Kontinental, respons bisa jauh lebih lambat karena hukumnya justru lahir dari regulasi tertulis seperti undang-undang.
Oleh karena itu, jangan heran jika transformasi digital dan platform raksasa sebagai big tech justru lahir dan berkembang pesat di AS sebagai penganut sistem Yurisprudensi.
Gagasan hukum transformatif adalah formulasi kolaboratif hibrida antara sistem Eropa Kontinental dan Common Law dalam menghadapi transfornasi digital dan Industry 5.0.
Salah satu landasannya adalah prinsip Lex Informatica sebagai salah satu sumber pembentukan hukumnya di samping konsep hukum pembangunan.
Formula hukum transformatif perlu digunakan agar hukum tidak semakin tertinggal dari realitas dan perkembangan teknologi yang berlari cepat.
Salah satu kelemahan sistem civil law adalah lamanya pembuatan perundang-undangan yang berakibat banyak perbuatan hukum yang tidak bisa ditangani secara proporsional. Bahkan di sisi lain terjadi kekosongam hukum, misalnya terkait dengan AI.
Konsep hukum transformatif memandang hukum tidak sekadar subtansi asas dan norma, tetapi juga proses pembentukannya, dampak terhadap teknologi, ekonomi dan ekosistem digital.
Hukum juga tidak hanya dipandang sebagai sebuah "static norms" yang bertujuan untuk terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian.
Hukum lebih jauh harus diproyeksikan sebagai infrastruktur transformasi untuk terciptanya kemanfaatan dan kemampuan negara bertransformasi.
Metode pembentukan hukum seperti Omnibus Law adalah salah satu implementasinya. Metode ini juga berhasil dipraktikan di berbagai negara dalam mengatasi ketertinggalan hukumnya.
https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2023/09/17/104620480/saat-emoji-thumbs-up-diakui-sebagai-persetujuan-kontrak-oleh