
Merenungkan Indonesia Melalui China

PADA bulan Agustus 1945, Mao Tse Tung (Mao Zedong) dan Zhou Enlai terbang dari Yan'An ke ibu kota Tiongkok di masa perang, Chongqing, untuk membahas hubungan antara Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan Partai KMT (Kuomintang) setelah berakhirnya Perang antara Tiongkok dengan Jepang.
Ditemani oleh duta besar Amerika Serikat, Patrick J. Hurley, Mao bergabung dengan Chiang Kai-shek untuk makan malam pada tanggal 27 Agustus 1945 (10 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia), yang merupakan pertemuan pertama di antara kedua pemimpin politik Tiongkok tersebut.
Setelah tujuh minggu negosiasi, kedua belah pihak berhasil menyepakati tujuan bersama untuk membangun demokrasi politik di Tiongkok dan menempatkan semua angkatan bersenjata Tiongkok di bawah komando Chiang Kai-shek.
Namun, sepanjang negosiasi, kontak senjata antara kedua belah pihak tak kunjung berhenti, bahkan semakin meningkat karena pasukan PKT terus mendapat serangan di kedua sisi, baik utara maupun selatan sungai Yangtze.
Mao akhirnya kembali ke Yan' An pada 11 Oktober 1945, diikuti pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh PKT dan KMT setelah itu, yang sekarang dikenal sebagai "Double Tenth Agreement."
Dalam kesepakatan itu, PKT dan KMT saling mengakui. Kedua pihak berencana membentuk pemerintahan koalisi.
Walaupun tujuan dari kesepakatan bersama tersebut sebenarnya hanyalah untuk menghindari berlanjutnya perang saudara.
Sayangnya, pemerintah nasionalis di bawah Chiang Kai-shek menolak mengakui daerah-daerah yang telah dikuasai oleh PKT.
Seiring berjalannya waktu, Chiang mulai tidak yakin dengan manfaat pernyataan bersama tersebut. Menurut dia, solusi militer adalah pilihan terbaik.
Begitu juga sebaliknya. Mao menggambarkan pernyataan bersama itu hanya sebagai "secarik kertas belaka."
Mao kemudian menceritakan kepada Joseph Stalin; petinggi Uni Soviet kala itu bahwa perang saudara "hampir tak terhindarkan."
Dan pada akhir Oktober 1945, hasilnya semakin jelas bahwa perjanjian itu akan berumur pendek, dan perang saudara dalam skala penuh akan segera dimulai kembali pada tahun 1946.
Gagalnya kesepakatan antara PKT dan KMT akhir Oktober dan awal November 1945 tersebut menyadarkan Amerika Serikat bahwa imperium komunis yang direpresentasikan oleh rezim Stalin sudah bukan lagi sekutu layaknya ketika mengalahkan Adolf Hitler di belahan Eropa.
Stalin mulai menebar pengaruh ke negara-negara baru yang juga ingin dikuasai Amerika Serikat.
Sepanjang negosiasi memang terlihat jelas bahwa Stalin ada di belakang Mao. Begitu juga sebaliknya, ada Amerika di belakang Chiang, sehingga kebuntuan negosiasi nyata akan berujung pada terjadinya perang saudara.
Keyakinan Amerika Serikat bahwa kubu komunis akan bertindak sama di negara-negara baru lainnya yang notabene ingin terlepas dari penjajah menyusutkan semangat Paman Sam dalam mendukung proses kemerdekaan penuh di negara-negara baru, termasuk Indonesia.
Jelang bulan November tahun 1945, setelah tampak jelas bahwa kubu komunis sudah berada di sisi yang berseberangan dengan kepentingan sekutu, Amerika Serikat mengurangi tekanannya kepada Belanda di Indonesia.
Amerika Serikat bahkan sangat jelas terkesan mendukung rencana Belanda yang ingin melakukan Agresi Militer untuk merebut kembali Indonesia, setelah Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pascaluluh lantaknya Hiroshima- Nagasaki, dan Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Pun Amerika bergeming saat Inggris melangsungkan serangan brutal di Surabaya pada tanggal 10 November 1945.
Amerika Serikat memang mendua sejak Presiden Franklin D. Roosevelt mulai berkuasa di Amerika Serikat pada tahun 1933.
Rasa antipati Roosevelt pada kekuatan imperial Inggris berpadu dengan kebijakan antiperang yang diwariskan pemerintahan Woodrow Wilson mendorongnya untuk berlarut-larut mencemplungkan diri ke dalam perang melawan Hitler di Eropa, meskipun berkali-kali diminta oleh Winston Churchil, perdana menteri Inggris.
Sampai akhirnya peristiwa Pearl Harbor memberi tanda yang jelas bahwa Amerika Serikat harus turun langsung dalam membantu baik Inggris dan Perancis, plus mengusir Jepang dari China.
Kemudian setelah Presiden Amerika Serikat ke-33 Harry S. Truman menggantikan Roosevelt, spirit perang kinetik berganti dengan spirit perang dingin.
Semangat antikomunis semakin jelas terlihat (doktrin Truman) di pihak sekutu yang melemahkan semangat Amerika Serikat untuk membebaskan koloni-koloni Inggris dan Belanda di wilayah Asia.
Ambiguitas Amerika Serikat tersebut membuat posisi pasukan Inggris (yang disertai pasukan dari India) lebih leluasa melakukan serangan brutal kepada militer dan rakyat Surabaya pada tanggal 10 November 1945, tak lama setelah negosiasi Mao dan Chiang gagal di Chongqing, di saat Inggris ingin melucuti senjata Jepang dan membebaskan pasukan sekutu di Surabaya.
Serangan brutal dan tak imbang tersebut, yang disambut dengan perjuangan heroik penuh keberanian oleh rakyat Indonesia di Surabaya, kini diperingati sebagai hari Pahlawan Nasional oleh Indonesia.
Posisi yang sama diperlihatkan Amerika Serikat di saat Belanda memutuskan ingin melancarkan Agresi Militer Belanda Pertama dan Kedua dua tahun kemudian.
Namun empat tahun setelah itu, karena semakin bergejolaknya gelora nasionalisme rakyat Indonesia (antikolonialisme), tekanan dunia internasional, dan keputusan Indonesia untuk memadamkan pemberontakan PKI di Madiun, yang berpadu dengan meningkatnya ancaman Stalin di Eropa serta kemenangan Mao atas Chiang Kai-shek di China (Chiang mundur ke Taiwan), memaksa Amerika Serikat harus menekan Belanda agar segera mengakui kemerdekaan Indonesia.
Di satu sisi, Amerika Serikat meyakinkan Amsterdam bahwa Indonesia tidak akan jatuh ke tangan komunis.
Di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutu memang membutuhkan tambahan pasukan untuk mengimbangi aksi penambahan pasukan Soviet di Jerman Timur.
Kemudian dua bulan setelah Mao mendeklarasikan People Republic of China (PRC), Belanda dan Indonesia memperoleh kata sepakat di Konfrensi Meja Bundar dengan beberapa syarat dan ketentuan.
Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Sementara urusan Papua Barat dibicarakan kemudian.
Namun perjuangan kemerdekaan, gelora nasionalisme, dan dialektika geopolitik yang begitu panjang tersebut tidak serta merta mengubah kemerdekaan menjadi surga untuk ibu pertiwi dan rakyat Indonesia.
Dialektika ekonomi, politik dan demokasi pascaproklamasi melahirkan instabilitas demokrasi dan kerentanan politik yang nyaris berpengaruh ke segala bidang.
Hingga akhirnya di penghujung tahun 1950-an, Soekarno harus mendeklarasikan dekrit presiden untuk mengakhiri era demokrasi kompetitif dan memulai era demokrasi terpimpin (guided democracy).
Keputusan tersebut akhirnya juga membawa Indonesia memasuki babak baru pemerintahan beberapa tahun kemudian, yakni Orde Baru, setelah didahului peristiwa kelam tahun 1965.
Selama 32 tahun selanjutnya, Indonesia berpindah dari demokrasi terpimpin kepada era demokrasi versi Orde Baru yang cenderung sangat diktatorial. Partai-partai difusi menjadi dua dan satu Golongan Karya.
Mafia Berkeley masuk gelanggang ekonomi, menguasai Bappenas, Kementerian Keuangan, dan beberapa kementerian lainnya.
Ekonomi akhirnya menggeliat karena sokongan perencanaan ekonomi yang cukup terukur dan karena diuntungkan oleh era Oil Booming tahun 1970-an.
Soeharto secara "setengah hati" mencoba mengikuti gaya "Developmental State" (meminjam istilah guru besar Universitas California, Berkeley, Prof. Chalmers Johnson) yang diterapkan di Jepang.
Hasilnya, pembangunan yang bergelimang KKN di mana para Oligar (guru besar ilmu politik Northwestern University Jeffrey A. Winters menyebutnya dengan Sultanic Oligarch) berhasil dijinakkan di bawah satu komando sang jenderal berbintang lima, Soeharto.
Tapi dibanding Mao (1949-1976), Soeharto terbilang berhasil melakukan transformasi ekonomi Indonesia secara signifikan.
Di saat Soeharto berhasil mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, China sedang dihadang bencana kelaparan akibat kebijakan Great Leap Forward Mao Tse Tung.
Tak sampai di situ, derita itu semakin menjadi-jadi di saat Mao meluncurkan Cultural Revolution.
China baru mulai membalik keadaan menjadi lebih baik setelah Mao meninggal dan Deng Xiaoping yang menggantikannya meluncurkan kebijakan pintu terbuka (Open Door Policy) pasca-1978.
China punya sejarah kelam tahun 1989, sebelas tahun sejak Deng berkuasa, akibat transisi menuju liberalisme ekonomi yang tersendat secara politik setelah Hu Yaobang meninggal yang berbarengan dengan tingginya inflasi, puncaknya mencapai 28 persen.
Kita mengenalnya dengan peristiwa Tiananmen atau "Tiananmen Square Massacre," di mana kerusuhan berujung dengan tumpahnya darah para mahasiswa dan demonstran pada 1989.
Deng tanpa segan-segan memerintahkan wali kota Shanghai kala itu, Jiang Zemin, untuk membereskan demonstrasi dengan tank-tank milik People Liberation Army, pada tanggal 15 April 1989.
Peristiwa tersebut menjadi wake-up call bagi China untuk mengetatkan ikat pinggang politik, menyiapkan supra dan infrastruktur politik yang kuat sebelum melakukan liberalisasi ekonomi, agar Partai tidak ambruk.
Dan dua tahun kemudian, China menyadari bahwa langkahnya benar. Karena di sisi lain, Partai Komunis Soviet ambruk tahun 1991 ketika mencoba mendorong liberalisasi ekonomi dan politik sekaligus.
China semakin yakin, ada imbas politik yang harus ditanggung jika serta-merta ekonomi dibuka.
Oleh karena itu, China mengambil jalan tengah, liberalisasi ekonomi secara gradual, yang dimulai kembali setelah tur Deng Xiaoping ke China bagian selatan (dikenal dengan Deng's southern tour) yang mematangkan status Kawasan Ekonomi Khusus di Shenzhen, Zhuhai, Guangzhou, dan kota lainnya.
Tapi jauh hari sebelum China mengalami shock politik atas liberalisasi ekonomi yang ditempuhnya, Indonesia lebih dahulu didatangi goncangan politik atas kebijakan liberalisasi investasi, yakni peristiwa Malari 15 Januari 1974, yang berbuah kerusuhan.
Sama seperti Partai Komunis China, Orde Baru mengetatkan ikat pinggang politik, menggasak para demonstran hingga korban berjatuhan.
Partai Komunis China bertahan, Orde Baru juga demikian. Pak Harto tak mampu digoyang kala itu.
Yang terjadi malah tujuh bulan kemudian, tepatnya 9 Agustus 1974, justru presiden Amerika Serikat yang mundur dari jabatannya, Richard Nixon, karena tersengat kasus Watergate.
Namun pada tahun 1997-1998, hegemoni Orde Baru dan Pak Harto tak mampu lagi menahan gejolak penolakan.
Orde Baru berakhir dan berganti dengan era reformasi yang berlanjut sampai hari ini. Dari Habbie berpindah ke Gus Dur.
Setelah Gus Dur 'dikudeta' secara halus, Megawati naik takhta. Kemudian, era demokrasi elektoral kompetitif dimulai setelah terpilihnya SBY sebagai presiden pertama via pemilihan langsung.
Tapi pergantian Orde Baru dengan Orde reformasi ternyata tidak serta merta mengubah watak ekonomi politik Indonesia.
Para oligar yang beralih dari kekuasaan monolitik Soeharto ke era pasar bebas politik ternyata pelan-pelan ikut mengubah wajah ekonomi politik reformasi menjadi sangat "menor oligarkis," sebagaimana yang kita rasakan hari ini.
Pertumbuhan ekonomi yang terbilang baik tak terlalu terdistribusi dengan rata. Mengikut rumusan ekonom Perancis Thomas Piketty, di Indonesia "return of investment" jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi (r > g).
Kenaikan tahunan IHSG jauh di atas angka pertumbuhan ekonomi sehingga kekayaan para pemilik modal berlipat.
Walhasil, pemerataan menjadi kurang terperhatikan. Sementara China, yang belum membuka pasar finansialnya kala itu, nyaris tidak terpengaruh oleh krisis finansial Asia tahun 1997.
Sejak 1992, China melaju kencang dengan raihan angka pertumbuhan ekonomi yang sangat mengagumkan.
Walhasil, China layak berbangga diri karena mampu mengangkat ratusan juta rakyatnya ke atas garis kemiskinan.
China mulai fokus pada liberalisasi ekonomi dengan ambisi pertumbuhan yang tinggi. China pun kemudian memindahkan Ibu kotanya. Pernah di Chongqing, Nanjing, lalu ke Beiping (Beijing).
Tapi bukan itu yang membuat China berhasil sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Tidak ada satupun kajian tentang transformasi ekonomi China yang mengatakan pemindahan ibu kota sebagai pemicunya. Tidak pernah saya temui kajian semacam itu.
Karena itu, untuk mengejar ketertinggalan dari China, saya yakin pemindahan Ibu kota bukanlah hanya itu sebagai salah satu strateginya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.





















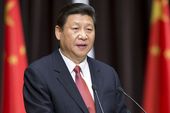













![[POPULER GLOBAL] Ekspor Senjata ke Israel | Tentara Ukraina Kecanduan Judi](https://asset.kompas.com/crops/h8sajibgSWSR3ekmZPiQq59uY3U=/0x0:1999x1333/177x117/data/photo/2023/12/21/6583b8707b3f6.jpg)





















