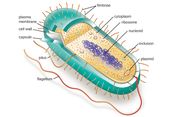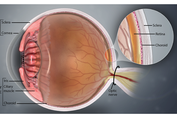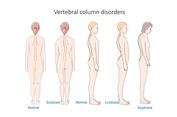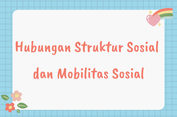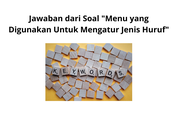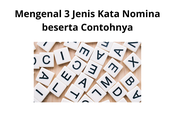Tari Serimpi, Tarian Klasik Yogyakarta

KOMPAS.com - Tari Serimpi merupakan salah satuan tarian Jawa klasik dari Kerajaan Mataram Islam di masa pemerintahan Sultan Agung.
Namun, seiring dengan adanya perjanjian Giyanti yang dilakukan pihak VOC dengan Sunan Pakubuana III pada 1755, Kerajaan Mataram pecah menjadi dua, yakni Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta berimbas pada tari Serimpi.
Di mana terjadi perbedaan gerakan pada dua kerajaan tersebut meski inti tariannya masih sama.
Dikutip situs Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), adapun jenis serimpi dari kedua keraton pewaris Mataram dapat dibedakan menjadi dua yakni, gaya Ngayogyakarta dan gaya Surakarta.
Fungsi tarian Serimpi pada masa lalu dipertunjukkan sebagai salah satu ritual sakral dalam acara-acara tertentu seperti pisowanan agung dan peringatan hari penting dalam keraton.
Tarian Serimpi yang dikenal pada masa Sultan Agung memang sama-sama dikenal oleh kedua kerajaan baru. Tapi dari keduanya memiliki sedikit perbedaan.
Baca juga: Tari Bedhaya Ketawang, Tarian Sakral Keraton Kasunanan Surakarta
Tari tersebut diperagakan empat putri yang masing-masing mendapat sebutan, air, api, angin dan bumi atau tanah. Selain melambangkan terjadinya manusia juga melambangkan empat penjuru mata angin.
Dikutip dari buku Seni Tari Jawa (1931) karya Lelyveld van Th. B, dulu tari Serimpi hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang pilihan keraton. Karena Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambang kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu, meski sifatnya tidak sesakral tari Bedhaya.
Tari Serimpi Gaya Yogyakarta
Dikutip dari buku Tari srimpi, Ekspresi Budaya Para Bangsawan Jawa (1994) karya Arif E. Suprihono, tari Serimpi dikenal di lingkungan budaya Jawa.
Di mana keberadaannya merupakan ungkapan seni komunitas bangsawan pada zaman keemasan raja-raja atau penguasa Jawa pada masa lalu.
Di lingkungan Keraton Yogyakarta ditemukan ada sejumlah 37 judul garapan dari Serimpi. Dari sejumlah besar nama Serimpi ada beberapa yang perpadanan nama dengan Serimpi yang ada di Surakarta.
Baca juga: Ciri-Ciri Umum Ras Negroid
Persamaan nama tersebut dapat diduga sebagai bentuk sajian yang sama atau juga sekedar persamaan nama tanpa kejajaran misi.
Dapat pula diduga bahwa nama itu sama oleh sebab diiringi oleh jenis gending yang sama.
Gerakan dalam Tari Serimpi ini didominasi oleh gerakan tangan, kaki, dan kepala.
Di lingkungan Keraton Yogyakarta, tari Serimpi dianggap sebagai salah satu tarian sakral disamping tari bedhaya dan wayang wong.