
Hutan Cadangan Pangan, Solusi bagi Ketahanan Pangan Nasional

SALAH satu ide cukup cemerlang dari Sumohadi, Menteri Kehutanan dan Perkebunan era Presiden Soeharto setelah dilantik menjadi menteri pada 16 Maret 1998, adalah menjadikan kawasan hutan sebagai basis ketahanan pangan untuk mendukung kecukupan dan ketahanan pangan nasional, khususnya padi dengan pola tumpangsari di lahan hutan.
Namun, ide itu tidak sempat terealisasi. Dua bulan kemudian, tepatnya 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri akibat gonjang ganjing politik. Kabinet Pembangunan VII, yang menaungi Sumohadi, juga bubar.
Masalah pangan, khususnya kecukupan beras, merupakan hal krusial bagi Indonesia. Seiring laju pertambahan penduduk yang pesat, yang belum diimbangi peningkatan laju produksi padi, Indonesia menjadi rawan pangan. Ketergantungan terhadap impor beras menjadi-jadi apabila terjadi anomali produksi di tingkat petani.
Di era Soeharto, dengan jumlah penduduk 125 juta jiwa, pernah mengalami zaman keemasan dalam mencukupi kebutuhan pangan penduduk, khususnya beras. Puncaknya tahun 1984, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang mampu berswasembada pangan, khususnya beras. Presiden Soeharto mendapatkan penghargaan dari FAO tahun 1984.
Baca juga: Ada Panen Raya di Pandeglang, Kementan Klaim Stok Beras Melimpah
Pada era Presiden BJ Habibie hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia menjadi negara importir beras, baik dari Thailand maupun Vietnam, untuk mencukupi kebutuhan pangan.
Tiga puluh delapan tahun kemudian (2021), dengan jumlah penduduk telah mencapai 270 juta jiwa, di era Presiden Joko Widodo, Indonesia baru mencetak sejarah lagi dengan mendapat penghargaan dari Institut Penelitian Padi Internasional (International Rice Research Institute/IRRI) karena Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021 secara berturut-turut.
IRRI menilai, Indonesia mencapai swasembada karena mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok domestik, dalam hal ini beras, lebih dari 90 persen. Upaya Presiden Jokowi membenahi sektor pertanian dengan membangun banyak infrastruktur pertanian (bendungan, embung, saluran irigasi) dari sejak awal pemerintahannya (2014 hingga kini 2022) tampaknya membuahkan hasil.
Akankah prestasi sebagai negara swasembada beras mampu dipertahankan untuk masa yang akan datang? Dengan kondisi agroklimat yang baik (lahan yang relatif subur dan iklim yang mendukung), seharusnya kita optimis dapat mempertahankan prestasi yang telah dicapai tiga tahun berturut turut tersebut, bahkan besaran produksi padinya masih dapat ditingkatkan dengan beberapa catatan-catatan sebagai berikut:
1. Mempertahankan Negara Agraris
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ada dua ciri-ciri negara agraris. Pertama, perekonomian bergantung pada sektor pertanian. Kedua, penduduknya mayoritas bermata pencarian di sektor pertanian. Pada masa Orde Baru, kedua ciri tersebut dimiliki Indonesia. Jadilah Indonesia negara agraris berdasarkan perhitungan kualitatif.
Seiring waktu berjalan, BPS tahun 2018 memaparkan berita resmi statistik mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menyatakan, Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi Indonesia adalah sektor industri, bukan pertanian. Sektor industri memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi 19,66 persen. Sektor pertanian justru berada pada posisi runner up dengan andil 13,53 persen.
Apabila negara agraris didefinisikan sebagai negara yang perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian, Indonesia sudah tidak pas lagi disebut sebagai negara agraris. Sektor yang memegang sumbangsih pertumbuhan ekonomi terbesar negara ini telah tergantikan dengan sektor industri.
Bahkan, semakin berkurangnya lahan pertanian akan lebih menurunkan share pertumbuhan ekonomi di Indonesia di masa mendatang, sehingga sektor potensial lain seperti perdagangan akan segera mengunggulinya.
Baca juga: Soal Pemerintah Impor Beras 500.000 Ton secara Bertahap, Gibran Pastikan Stok Beras di Solo Aman
Namun, apabila negara agraris adalah yang penduduknya mayoritas bermata pencarian di sektor pertanian, maka Indonesia masih relevan disebut negara agraris. Walaupun andil PDB sektor pertanian berada di posisi kedua, sektor pertanian merupakan sektor padat karya yang efektif menurunkan jumlah penganggur.
Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2018, sekitar 28,79 persen penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian sebagai pekerjaan utama. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, disusul sektor perdagangan (18,61 persen), dan sektor industri (14,72 persen).
Meskipun lahan pertaniannya yang dapat diolah seluah 55 juta hektare, namun luas lahan baku sawah hanya sekitar 7,46 juta hektare pada 2019.
Dwi Andreas Santosa, guru besar Fakultas Pertanian IPB menyebutkkan, meski ada program perluasan sawah dan food estate, luas lahan baku sawah semakin menyusut. Pada 2013 luas lahan baku sawah 8,13 juta hektare, empat tahun kemudian menjadi 7,75 juta hektare. Luas ini terus menyusut menjadi 7,11 juta hektare pada 2018 dan terakhir 7,46 juta hektare pada 2019.
Untuk mempertahankan swasembada beras, luas baku sawah 7,46 juta hektare harus tetap dipertahankan oleh pemerintah bagaimanapun caranya. Syukur-syukur mampu menambah luas baku sawah maupun budidaya padi lahan kering melalui ekstensifikasi yang memang dimungkinkan melalui pencetakan sawah baru, food estate, maupun program yang lainnya.
 Panen padi sawah di Desa Namang, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, pekan lalu. *** Local Caption *** Panen padi sawah di Desa Namang, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, pekan lalu.2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sawah
Panen padi sawah di Desa Namang, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, pekan lalu. *** Local Caption *** Panen padi sawah di Desa Namang, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, pekan lalu.2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sawah
 Panen padi sawah di Desa Namang, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, pekan lalu. *** Local Caption *** Panen padi sawah di Desa Namang, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, pekan lalu.
Panen padi sawah di Desa Namang, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, pekan lalu. *** Local Caption *** Panen padi sawah di Desa Namang, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, pekan lalu.Sejak Joko Widodo memerintahan delapan tahun lalu (2014) hingga saat ini, infrastruktur di bidang pertanian ikut dibangun. Tercatat 29 bendungan telah diresmikan dan tahun ini akan selesai lagi 38 bendungan. Targetnya sampai tahun 2024 ada lebih dari 61 bendungan dibangun.
Pemerintah juga membangun 4.500 embung, 1,1 juta km jaringan irigasi dan pemanfaatan varietas unggul padi selama tujuh tahun terakhir. Infrastruktur pertanian berupa bendungan dan jaringan irigasi ini membuka peluang intensifikasi luas baku lahan sawah yang tadinya panen sekali setahun menjadi tiga kali setahun.
Di samping itu dapat memperluas pencetakan sawah baru (ekstensifikasi) sepanjang dapat dijangkau oleh sarana jaringan irigasi yang baru dibangun.
BPS mencatat data otoritas statistik yang menyatakan Indonesia secara terus-menerus mengimpor beras sejak tahun 2000 hingga 2019. Data tersebut menggambarkan bahwa telah terjadi impor beras sepanjang periode kepemimpinan Jokowi sejak 2014 hingga 2019.
Pada 2019, Indonesia tercatat mengimpor beras sebanyak 444.508 ton atau setara 184,2 juta dolar AS. Beras asal Pakistan menjadi paling banyak diimpor, sebanyak 182.564 ton. Tetapi beras yang diimpor tersebut merupakan beras khusus, bukan beras medium yang kita konsumsi sehari-hari.
Produksi beras Indonesia tahun 2019 mencapai 31,31 juta ton, tahun 2020 sebanyak 31,50 juta ton dan tahun 2021 mencapai 31,36 juta ton. Menurut perhitungan BPS, stok padi di lapangan pada akhir April 2022 sejumlah 10,2 juta ton.
Data dan fakta inilah yang membuat IRRI memberikan penghargaan. Indonesia disebut telah memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada pangan.
3. FOLU Net Sink 2030 Harus Berhasil
Kini muncul ancaman krisis pangan global akibat krisis iklim yang melanda Bumi ini. Krisis iklim menjadi ancaman yang akan mengganggu peningkatan produksi padi Indonesia. Karena itu, mitigasi perlu terus dilakukan agar swasembada bisa berlanjut pada tahun-tahun mendatang.
FoLU (Forest and Other Land Use) Net Sink 2030 harus berhasil untuk mengamankan swasembada pangan. FOLU Net Sink berarti penyerapan gas rumah kaca (GRK) sudah sama atau lebih banyak dibandingkan dengan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
FOLU Net Sink 2030 menjadi kata kunci dalam pengendalian perubahan dan krisis iklim. Indonesia berkomitmen mencapai FOLU Net Sink pada 2030. Dalam FOLU Net Sink, penyerapan GRK dari sektor kehutanan ditargetkan 140 juta ton CO2e pada 2030 dan meningkat menjadi 304 juta ton setara CO2 pada 2050.
Sektor kehutanan hendak menurunkan emisi GRK 17,2 persen dari 2,87 miliar ton perkiraan emisi 2030 dalam skenario penurunan emisi nasional 29 persen. Menurut dokumen nationally determined contributions (NDC) atau kontribusi nasional yang baru ditetapkan, deforestasi akumulatif yang diizinkan dalam skenario menurunkan emisi 29 persen seluas 6,8 juta hektare pada 2030.
Artinya, deforestasi yang diizinkan maksimal 680.000 hektare per tahun. Selain mencegah deforestasi, pemerintah juga hendak meluaskan areal lindung di kawasan hutan.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, areal lindung akan dinaikkan dari 51,8 juta hektare menjadi 65,3 juta hektare. Restorasi dan reforestasi juga dinaikkan.
Dalam dokumen NDC baru, target rehabilitasi hutan tak produktif seluas 12 juta hektare dan penanaman pohon pada areal 230.000 hektare per tahun. Sementara target restorasi rawa gambut seluas 2 juta hektare dengan asumsi keberhasilannya 90 persen.
Untuk memastikan FOLU Net Sink tercapai, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah menandatangani dokumen Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Dokumen Rencana Operasional ini memandu apa yang harus dilaksanakan semua aktor secara kolaboratif.
Delapan kebijakan ditetapkan, di antaranya yang penting adalah pencegahan/penurunan laju deforestasi hutan, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut dan mangrove.
Realistiskah mengurangi target emisi dalam waktu 7,5 tahun lagi? Target itu tampaknya sulit dilaksanakan kalau hanya mengandalkan unit kerja lingkup KLHK. Target pengurangan emisi karbon dalam FOLU Net Sink 2030 menjadi kurang realistis jika tidak dikolaborasikan dengan pemangku kepentingan: pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, dan masyarakat, melalui kerja program struktural, kemitraan, dan pembinaan kemasyarakatan.
4. Hutan Cadangan Pangan
Untuk meningkatkan produksi padi dalam mempertahankan swasembada beras, sebenarnya pemerintah tidak saja mengandalkan hasil produksi padi dari lahan baku sawah, tetapi juga memanfaatkan hasil padi dari lahan kering. Kegiatan perhutanan sosial sebagai bagian dari program reforma agraria yang memberi akses kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk meningkat produksi padi melalui budidaya padi di lahan kering pada lahan-lahan dalam kawasan kegiatan perhutanan sosial.
Dari total target perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare sampai hari ini realisasinya telah mencapai 5 juta hektare. Potensinya sangat besar, dari target luas perhutanan sosial 12,7 juta ha, 50 persennya saja (kurang lebih 6 juta ha) ditanami padi lahan kering dengan sistem tumpangsari akan menghasilkan padi 18 juta ton brutto (asumsi 1 ha menghasilkan 3 ton padi) setiap kali panen.
IPB University meluncurkan varietas padi terbaru, yaitu padi 9G IPB. Ini temuan baru IPB atas padi unggul berupa padi gogo atau padi lahan kering. Varietas padi IPB 9G memiliki potensi hasil pada lahan darat mencapai 9,09 ton per hektare dengan produktivitas rata-rata 6,09 ton per hektare.
Dengan varietas baru dari IPB itu, hasil bruto padi lahan kering dari lahan perhutanan sosial dapat mencapai 36 juta ton. Masalahnya adalah lahan yang disiapkan untuk kegiatan perhutanan sosial tidak semuanya layak untuk tanaman padi lahan kering.
Untuk lahan perhutanan sosial di Jawa dan sebagian Sumatera barangkali bisa dimanfaatkan. Namun tidak bagi lahan di Kalimantan dan sebagian Sumatera karena lahan hutannya berupa lahan gambut.
Karena itu KLHK bersama sama Kementerian Pertanian sebaiknya melakukan pemetaan untuk memilah-milah kelayakan lahan hutan yang ada.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.-
![]()
Pengamat Kritisi Perpres Cadangan Pangan yang Diterbitkan Jokowi
-
![]()
Jokowi Terbitkan Perpres Cadangan Pangan, Ini Respons Bulog
-
![]()
Ini Jenis-jenis Ikan yang Bakal Diatur Pemerintah untuk Cadangan Pangan
-
![]()
ID FOOD Siapkan Sistem "Supply Chain Control Tower" untuk Optimalkan Program Cadangan Pangan Pemerintah
-
![]()
Tahun Ini BUMN Pangan Bakal Urus Cadangan Pangan Pemerintah
-
![]()
Pastikan Stok Beras Nasional Cukup, Mentan SYL: Kita Percaya Data BPS
-
![]()
Kata Mentan Stok Beras Surplus, Tapi Kok Impor?
-
![]()
Debat Panas Stok Beras Kementan Vs Bulog, Jokowi sampai Turun Tangan
-
![]()
Jelang Natal dan Tahun Baru, Stok Beras di Bangka Belitung Surplus











































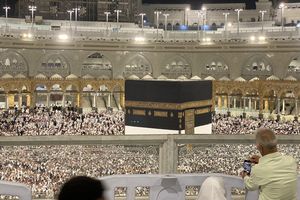



![[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang](https://asset.kompas.com/crops/fRPgCbfHo5wgxsjG-uv04uLabWQ=/0x0:0x0/300x200/data/photo/2024/06/14/666becf29e5f6.jpeg)












