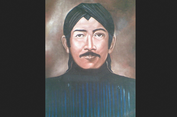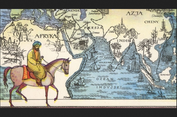Sekularisasi Gagal atau Model Baru?
Bisa saja kita berkaca ke sejarah China, Mesir, Jepang, Korea, atau Amerika Latin. Sah-sah saja.
Namun arti penting sejarah awal demokratisasi, revolusi industri, dan perubahan sosial dan politik tidak bisa dilepaskan dari perjalanan bangsa-bangsa Eropa yang mengalami gonjang-ganjing dan rela dijadikan model percobaan-percobaan.
Di sanalah berbagai kegagalan dan harapan dimulai. Negara-negara modern pasca-Perang Dunia II memodifikasi sampel.
Dari situ refleksi dan penemuan cara bermasyarakat dan bernegara di dunia bertumpu. Eropa mempunyai khazanah yang baik dan buruk untuk berkaca pada sejarah sendiri.
Sebetulnya, membaca sejarah bangsa lain itu berarti juga menimbang-nimbang sejarah sendiri. Itu juga dilakukan oleh para pemikir Eropa waktu itu dan Amerika masa kini.
Mereka belajar Mesir kuno, China, Timur Tengah, dan Asia Tenggara untuk menjadi bahan bagi kemajuan bangsa sendiri.
Para ilmuan dan cendikiawan Eropa dan Amerika menguasai pengetahuan di luar dua benua itu, karena itu mereka belajar masyarakat lain dan otomatis masyarakat sendiri.
Bagaimana agama diposisikan di Eropa bisa menjadi pelajaran berharga bagi bangsa lain.
Sekularisasi sudah menjadi tema panjang Indonesia sejak bangsa ini didirikan. Sukarno, Hatta, Agus Salim, Cokroaminoto, Supomo, Yamin semua membahasnya tanpa ragu-ragu. Dan mereka sudah mengantisipasi itu lewat jalan tengah.
Menurut rumusan para pendiri bangsa ini, sekuler yang tidak melupakan agama. Taat agama, tetapi sekuler dalam bernegara. Moderat dan jalan tengah jawabannya.
Filosofi sekularisasi sebetulnya bertumpu tidak hanya pada terjadinya pemisahan antara agama dan politik, gereja dan istana, masjid dan sultan, pure dan raja.
Namun sekularisasi juga adalah upaya memahami bagaimana kontrak sosial ditempatkan. Kontrak sosial, yang berisi kontrak politik antara penguasa dan rakyat, adalah kontrak non-religius, non-samawi, dan non-ukhrawi.
Kontrak sosial itu dilakukan antarmanusia, tanpa melibatkan Tuhan, agama, dan langit. Kontrak itu terjadi di bumi yang bisa dihukumi secara hukum bumi juga.
Pemerintah dipilih oleh rakyat, bukan Tuhan. Pemerintah silih berganti gilirannya dan ada masanya, tidak abadi seperti urusan langit dan ketuhanan. Itulah cara memahami sekularisasi yang sederhana.
Sekularisasi sebetulnya adalah proyek panjang dalam sejarah dan belum selesai. Konsep seperti dipahami oleh filosof Jerman, Juergen Habermas yang memaknai sekularisasi adalah wacana terbuka.
Namun bagi sebagian pemikir tradisi Amerika kritis, sekularisasi perlu ditinjau ulang, seperti Peter Berger. Sekularisasi telah gagal. Sekularisasi tidak lagi tepat saat ini.
Manusia berpolitik dan hidup bermasyarakat ternyata tidak bisa melepaskan diri dari unsur agama. Agama tetap hadir dan tidak bisa dihilangkan.
Di Indonesia praktiknya, memang hukum dan peraturan negara kita disahkan lembaga legislatif dan dilaksanakan oleh yudikatif, dan bukan kembali ke Kitab Suci agama-agama yang enam itu. Itu bentuk sekularisasi.
Hukum dari manusia, bukan Tuhan. Secara formal dan legal begitu. Pemilu juga proses manusia di bilik suara, bukan ritual dan ibadah di tempat ibadah. Penentuan kemenangan juga dengan penghitungan suara, bukan bertasbih.
Tetapi praktiknya tidak begitu saja, agama tidak lalu hilang dari proses-proses politik. Bahasa agama tetap hadir dan bermanfaat.
Setelah Indonesia merdeka, penggunaan bahasa agama lebih mudah dipahami, baik oleh pemimpin ataupun rakyat. Berbagai isu politik menggunakan bahasa agama.
Kata demokrasi dibahasakan dengan contoh-contoh dalam ajaran agama, baik ayat-ayat Kitab Suci ataupun tradisi agama.
Banyak program pemerintah Orde Baru dikomunikasi ke rakyat dengan bahasa agama, seperti Keluarga Berencana (KB) diartikan sebagai keluarga bahagia (sakinah).
Dalam ranah politik praktis, partai-partai di Indonesia tetap yang terikat dengan sentimen agama. Tentu itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa.
Nyatanya, tidak ada partai politik Indonesia yang benar-benar agamis, pasti ada sisi nasionalisnya.
Begitu juga tidak ada partai politik yang benar-benar nasionalis, pasti mengakomodasi unsur-unsur agamisnya.
Bahkan kecenderungan penyeragaman ideologi dan kesamaan sikap banyak partai politik di Indonesia terasa. Mana nasionalis, mana religious, mana konservatif, mana tradisionalis, mana progresif, semua terasa bercampur seperti gado-gado dan saling mengakomodasi. Garis antara agamis dan nasionalis kabur.
Tidak hanya di Indonesia, di Amerika agama pun tetap hadir. Partai Republik, partai yang menjadi tumpuan presiden Donald Trump, menggunakan sentimen keagamaan Kristen Protestan.
Konservatisme, baik sentimen agama maupun nasionalisme sempit dihembuskan, mengatarkan Trump menjadi presiden.
Di Jerman dengan sentimen moderat CDU (Christlich Demokratische Union/Partai Demokratik Kristiani) berkoalisi dengan CSU (Christlich Social Union/Partai Kristen Sosial Bavaria) dan SPD (Partai Sosial Demokrat) mendukung Kanselor Angela Merkel.
Singkatnya, sentimen kelompok keagamaan masih hadir di negara-negera yang menyatakan diri sekuler dan menjadi model sekularisasi di dunia.
Apakah sekularisasi, yang menekankan absennya agama di ruang politik dan publik, gagal? Ataukah sekularisasi kini sudah dimodifkiasi menjadi sekulariasi yang memberi ruang faktor-faktor keagamaan?
Di Indonesia tidak mungkin meninggalkan faktor agama. Jelas, jangankan partai politik yang mendulang sentimen kelompok keagamaan, partai yang nasionalis pun mengkomodasi simbol-simbol agama.
Bagaimana sebetulnya nasib sekularisasi di dunia dan di Indonesia? Tergantung memandangnya, bisa jadi sekularisasi gagal, bisa juga sekulariasi telah berevolusi ramah pada agama.
https://www.kompas.com/stori/read/2023/12/21/103350879/sekularisasi-gagal-atau-model-baru