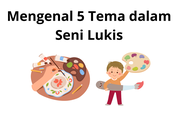Cultuurstelsel, Sistem Tanam Paksa yang Sengsarakan Rakyat Pribumi

KOMPAS.com - Sistem tanam paksa atau cultuurstelsel menjadi bagian pilu dari sejarah penjajahan Indonesia.
Dilansir dari Encyclopaedia Britannica (2015), cultuurstelsel atau sistem tanam paksa adalah kebijakan Pemerintah Hindia Belanda memaksa para petani pribumi menyisihkan sebagian lahannya untuk ditanami komoditas ekspor atau bekerja suka rela menggarap tanah pemerintah.
 Potret Gubernur Jendral Hindia Belanda Johannes Graaf van den Bosch (1780-1844) dilukis oleh Raden Saleh pada 1811 ?1880.
Potret Gubernur Jendral Hindia Belanda Johannes Graaf van den Bosch (1780-1844) dilukis oleh Raden Saleh pada 1811 ?1880.Komoditas yang dimaksud di antaranya gula, kopi, serta nila atau tarum. Tanaman ini ditanam di samping padi yang digarap petani.
Baca juga: Sejarah Tempe, Makanan Kaya Protein yang Lahir dari Era Tanam Paksa
Yang tak punya di sawah, diminta bekerja menggarap lahan milik Pemerintah Hindia Belanda. Lama masa kerja mencapai seperlima tahun atau 66 hari.
Tanah yang dialokasikan untuk komoditas ekspor, tidak dikenakan pajak. Petani baru mendapat keuntungan jika hasil tanaman nilainya lebih dari nilai pajak yang dibebaskan.
Namun jika gagal panen, maka petani harus mengganti rugi. Risiko gagal panen hanya ditanggung pemerintah jika disebabkan hal-hal di luar kelalaian petaninya.
Menyengsarakan rakyat
Sistem tanam paksa tak berjalan sesuai niat awalnya. Rakyat disengsarakan dengan sistem ini.
Baca juga: Budi Utomo, Sejarah Berdirinya dan Peranannya
Hukum tertulis menyebut rakyat mengalokasikan lahannya secara sukarela. Namun dalam praktiknya, rakyat dipaksa.
Ketentuan seperlima lahan atau 66 hari kerja, nyatanya diminta lebih oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Rakyat juga dibuat kesulitan dengan tanggung jawab mengirim hasil komoditas tanam paksa. Kala itu, belum ada sarana transportasi logistik.
Jika gagal panen, rakyat tetap yang harus menanggung. Mereka yang sudah kena kewajiban tanam paksa, masih harus membayar pajak.
Baca juga: Kisah Sukses Belanda Jadi Eksportir Makanan Terbesar Kedua di Dunia
Dikutip dari Tanah dan Tenaga Kerja (1992), sistem tanam paksa menyimpang dari yang dijanjikan Gubernur Jendral van den Bosch.
Penyimpangan itu muncul dalam bentuk cultuurprocenten. Cultuurprocenten adalah pemberian untung kepada petugas apabila hasil yang dicapai melebihi target produksi yang telah ditentukan pada setiap desa.
Petugas yang ditunjuk pemerintah Belanda yakni penguasa pribumi dan bupati atau kepala daerah.
Pemberian premi yang dimaksudkan agar para petugas itu bekerja dengan baik, ternyata disalahgunakan. Tenaga petani diperas demi mengejar premi sebanyak-banyaknya.
Baca juga: Sejarah Cokelat Bisa Ditemui di Indonesia
Multatuli
Derita yang dirasakan rakyat pribumi akibat cultuurstelsel, ditentang banyak orang dari Belanda sendiri. Di pertengahan 1850-an, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda kebanjiran kritik.
Salah satu kritik paling keras datang dari penulis Eduard Douwes Dekker. Douwes Dekker mengkritiknya lewat roman tentang sistem tanam paksa di Lebak, Banten.
Agar selamat dari persekusi Belanda, Douwes Dekker menggunakan nama samaran Multatuli. Karyanya itu diterbitkan pada 1860 dengan judul Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij (Max Havelaar, atau Lelang Kopi Perusahaan Dagang Belanda).
Kritik dari Douwes Dekker dan warga Belanda lainnya baru didengar Pemerintah Hindia Belanda pada 1870.
Cultuurstelsel atau tanam paksa dihentikan setelah dikritik keras. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan UU Agraria pada 1870 dan UU Gula pada 1870, yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia.
Baca juga: Meratapi Rumah Multatuli
Sistem tanam paksa telah memajukan perekonomian dan perdagangan Belanda. Selama tanam paksa diberlakukan antara 1830-1877, rakyat pribumi telah memperkaya Belanda hingga 823 juta gulden atau setara dengan Rp 6,8 triliun berdasarkan kurs Desember 2019.
Sebagai ganjaran, Gubernur Jenderal van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar Graaf oleh Raja Belanda pada 25 Desember 1839.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.-
![]()
Fahri Hamzah Kembali Desak PKS Bayar Ganti Rugi Rp 30 Miliar
-
![]()
Kementan Berhasil Buka Lahan Cetak Sawah Seluas 1,16 Juta Hektar
-
![]()
Tumbuhkan Minat Generasi Milenial Menjadi Agrosociopreneur Sukses
-
![]()
Mini Agrowisata, Primadona Wisata Edukasi Pertanian di Surabaya
-
![]()
Hari Ini dalam Sejarah: Pertempuran 10 November dan Berbagai Pemicunya
-
![]()
Hari Pahlawan, Ini Kisah Empat Perempuan Belanda Pembela Indonesia